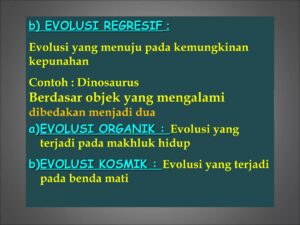Mengapa masyarakat Indonesia tidak peduli pada kegiatan politik pemerintah? Pertanyaan ini kerap menggelayuti ruang diskusi, namun jawabannya tidak sesederhana sekadar malas atau acuh. Ada lapisan-lapisan kompleks yang berakar dari sejarah, terpupuk oleh budaya, dan diperkuat oleh realitas ekonomi sehari-hari. Fenomena apatisme politik ini bukanlah sebuah keanehan, melainkan respons yang dapat dipetakan dari pengalaman kolektif bangsa.
Dari warisan trauma Orde Baru yang membungkam suara kritis, hingga kesibukan memenuhi kebutuhan pokok yang tak kunjung usai, jarak antara warga negara dan arena politik formal semakin menganga. Politik sering kali dirasakan sebagai panggung elite yang berisik, sementara urusan perut dan rasa aman di lingkungan terdekat justru menuntut perhatian lebih nyata dan mendesak.
Latar Belakang Historis dan Sosial Budaya
Untuk memahami sikap apatis politik yang tampak hari ini, kita perlu menengok ke belakang. Persepsi masyarakat terhadap politik tidak terbentuk dalam ruang hampa, melainkan dipahat oleh pengalaman kolektif sejarah dan nilai-nilai budaya yang mengakar. Warisan dari rezim-rezim sebelumnya, khususnya Orde Baru, masih membayangi cara banyak orang memandang partisipasi politik, sementara struktur sosial budaya sering kali mengutamakan harmoni dan kepatuhan daripada kritik terbuka.
Warisan Politik Orde Baru dan Transmisi Keluarga

Source: maritimefairtrade.org
Selama 32 tahun, rezim Orde Baru menjalankan sistem politik yang sangat terkontrol, di mana partisipasi masyarakat dibatasi pada ritual pemilu lima tahunan dengan hasil yang sudah dapat diprediksi. Politik diasosiasikan dengan hal yang berbahaya, penuh intrik, dan domain eksklusif negara. Trauma terhadap represi dan depolitisasi massal pada era itu telah menciptakan generasi yang memilih untuk “hidup aman” dengan menjauh dari urusan politik.
Fenomena apatisme politik di Indonesia seringkali berakar pada persepsi bahwa narasi kebijakan publik ibarat dongeng yang sulit dipetakan—mirip seperti saat kita mencoba Menentukan Tahap Cerita Fabel pada Paragraf Terbakar. Ketika alur cerita terasa dipaksakan dan pesan moralnya kabur, publik memilih untuk menjauh. Mereka merasa tak lagi punya alat untuk membedakan mana konflik, klimaks, atau resolusi dalam drama politik yang setiap hari mereka saksikan, sehingga akhirnya memilih untuk tidak peduli.
Sikap ini kemudian ditransmisikan dalam keluarga, di mana orang tua sering menasihati anaknya untuk fokus pada sekolah dan kerja, bukan berpolitik, karena dianggap tidak membawa manfaat nyata dan penuh risiko.
Nilai-nilai budaya seperti “ewuh pakewuh” (sungkan), menjunjung tinggi otoritas, dan menjaga ketertiban sosial juga berperan. Mengkritik pemerintah atau terlibat dalam aksi protes sering dilihat sebagai perbuatan yang tidak sopan dan mengganggu kerukunan. Politik dipandang sebagai arena yang kotor dan tabu, sehingga lebih baik dihindari.
| Periode Sejarah | Ciri Dominan Sistem Politik | Pola Partisipasi Publik | Dampak pada Sikap Apatis Masa Kini |
|---|---|---|---|
| Orde Lama | Politik sangat ideologis dan dinamis, penuh gejolak. | Mobilisasi massa tinggi, namun sering berujung konflik. | Menciptakan nostalgia sekaligus kelelahan terhadap politik yang dianggap ‘ribut’ dan tidak stabil. |
| Orde Baru | Politik sangat terkontrol, sentralistik, dan represif. | Partisipasi semu, hanya sebagai ritual. Ruang publik dibungkam. | Membentuk trauma kolektif, ketakutan, dan persepsi bahwa politik adalah urusan penguasa yang berbahaya. |
| Era Reformasi | Demokratisasi, desentralisasi, kebebasan berpendapat. | Kebebasan berekspresi tinggi, tetapi diiringi disorientasi dan kekecewaan. | Kebebasan yang membanjir justru memicu kelelahan informasi. Kekecewaan berulang mengonfirmasi sikap apatis warisan Orde Baru. |
Faktor Ekonomi dan Kesejahteraan
Bagi sebagian besar masyarakat, politik adalah kemewahan. Ketika pertaruhan harian adalah memastikan ada nasi di meja, biaya sekolah anak terbayar, dan cicilan tidak menunggak, isu-isu seperti revisi undang-undang atau koalisi partai terasa sangat jauh dari realitas. Prioritas hidup yang bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar ini secara alami menggeser perhatian dari arena politik, yang hasilnya sering kali tidak langsung terasa.
Prioritas Ekonomi dan Kesenjangan yang Melebar
Kesenjangan ekonomi yang nyata memperkuat persepsi bahwa politik adalah permainan elit. Ketika para politikus berkampanye dengan mobil mewah dan janji muluk, sementara konstituennya berjuang naik angkutan umum yang mahal, terbentuk jarak psikologis yang lebar. Masyarakat awam merasa bahwa sistem politik tidak dirancang untuk mereka, melainkan untuk menjaga kepentingan kelompok yang sudah mapan. Tekanan finansial menjadi penyedot perhatian utama, yang membuat energi kognitif untuk memikirkan politik menjadi sangat terbatas.
- Waktu yang Terbatas: Bagi pekerja dengan jam kerja panjang atau mereka yang bekerja serabutan, waktu luang adalah barang mewah. Waktu itu lebih sering digunakan untuk istirahat atau keluarga daripada untuk mengikuti perkembangan politik.
- Biaya Opportunitas: Menghadiri diskusi atau aksi sosial politik berarti kehilangan waktu yang bisa digunakan untuk mencari penghasilan tambahan. Bagi banyak orang, pilihan ini jelas tidak menguntungkan.
- Kebutuhan Langsung vs Manfaat Tidak Pasti: Memperjuangkan kenaikan upah melalui demonstrasi mungkin memberikan manfaat di masa depan, tetapi kebutuhan membeli beras dan minyak adalah hari ini. Politik kalah telak oleh urusan perut.
“Urusan perut rakyat jangan dijadikan bahan politik.” Kalimat yang sering diucapkan publik figur ini justru mengungkap sebuah paradoks: bahwa dalam benak banyak orang, politik di satu sisi, dan urusan perut (kesejahteraan) di sisi lain, adalah dua hal yang terpisah dan tidak berhubungan.
Persepsi terhadap Sistem dan Aktor Politik
Kekecewaan adalah ibu dari ketidakpedulian. Ketika harapan berulang kali dibenturkan pada realitas korupsi, janji kampanye yang menguap, dan kebijakan yang tidak populer, masyarakat mengembangkan mekanisme pertahanan diri: masa bodoh. Sikap ini bukan lagi sekadar ketidaktahuan, melainkan pilihan sadar untuk tidak peduli sebagai bentuk protes pasif terhadap sistem yang dianggap gagal memenuhi harapannya.
Kekecewaan Berulang dan Kompleksitas Birokrasi, Mengapa masyarakat Indonesia tidak peduli pada kegiatan politik pemerintah
Setiap kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, setiap wakil rakyat yang tiba-tiba “hilang” setelah terpilih, dan setiap kebijakan yang dirasakan menyusahkan rakyat kecil, adalah paku yang menancap dalam memori kolektif. Ini diperparah oleh birokrasi yang berbelit dan prosedur politik yang terasa sangat rumit bagi orang awam. Rasa “tidak mampu” memahami mekanisme ini berubah menjadi rasa “tidak mau” terlibat. Media, di sisi lain, sering kali memperkuat citra negatif ini dengan pemberitaan yang sensasional tentang konflik dan skandal, ketimbang mendalam pada substansi kebijakan.
| Jenis Kekecewaan Politik | Contoh Manifestasi | Efek pada Persepsi Publik | Dampak pada Tingkat Kepedulian |
|---|---|---|---|
| Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan | Kasus korupsji di lembaga seperti KPK, Kemendikbud, atau pemerintah daerah. | Memperkuat stereotip “semua politikus korup” dan politik sebagai ladang mencari rente. | Menurunkan kepercayaan secara drastis. Muncul anggapan “buat apa peduli, ujung-ujungnya korupsi juga.” |
| Janji Palsu (Janji Kampanye) | Janji membangun fasilitas umum atau menurunkan harga sembako yang tidak terealisasi. | Menciptakan sinisme terhadap seluruh proses politik dan kampanye. | Membuat masyarakat mengabaikan seluruh narasi politik, dianggap sebagai “jualan mimpi” belaka. |
| Kebijakan Tidak Populer | Kenaikan harga BBM, pajak, atau aturan yang dirasa memberatkan rakyat kecil. | Memunculkan perasaan dikhianati dan tidak diwakili oleh pemerintah yang mereka pilih. | Memicu ketidakpedulian aktif, berupa penolakan untuk terlibat dalam proses politik berikutnya. |
Akses Informasi dan Lingkungan Media: Mengapa Masyarakat Indonesia Tidak Peduli Pada Kegiatan Politik Pemerintah
Di era digital, informasi politik seharusnya lebih mudah diakses. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: banjir informasi, disinformasi, dan konten yang sensasional sering kali membuat masyarakat kebingungan dan akhirnya lelah. Politik di media sosial sering direduksi menjadi perang meme, caci maki, dan debat kusir yang tidak substansial. Hal ini justru menjauhkan orang dari politik yang substantif.
Banjir Informasi dan Konten yang Menjauhkan
Tantangannya bukan lagi kekurangan informasi, tetapi kesulitan menemukan informasi yang akurat, mudah dicerna, dan relevan dengan konteks lokal warga. Banyak berita politik yang disajikan dengan bahasa hukum yang kaku atau hanya membahas dinamika elit di Jakarta, yang tidak terkait langsung dengan masalah jalan rusak di kampung atau harga pupuk di desa. Di tengah kesibukan, masyarakat kemudian memilih mengonsumsi konten yang lebih menghibur atau praktis.
- Konten Konflik dan Drama: Pemberitaan lebih fokus pada cekcok antar politikus, gaya hidup mereka, atau skandal pribadi, daripada analisis kebijakan. Politik dilihat sebagai sinetron yang melelahkan.
- Misinformasi dan Hoaks: Banjir informasi yang tidak terverifikasi menciptakan kebingungan. Ketidakmampuan membedakan fakta dan hoaks membuat orang memilih untuk tidak percaya pada semua informasi, atau menarik diri sama sekali.
- Eko Chamber dan Polarisasi: Algoritma media sosial menjebak pengguna dalam gelembung pendapat yang sama. Ini bisa membuat mereka yang tidak tertarik politik merasa informasi yang muncul tidak relevan, sehingga makin mengabaikannya.
“Politik itu kotor dan ribet. Daripada mikirin itu, mending kita fokus kerja dan urus keluarga.” Narasi seperti ini sangat umum ditemui di kolom komentar media sosial atau obrolan warung kopi. Ia menggambarkan politik sebagai ranah yang secara inheren negatif dan tidak penting dibandingkan dengan urusan “nyata” dalam hidup.
Fenomena apatisme politik di Indonesia bisa jadi berakar dari pola interaksi sosial kita yang paling dasar. Sebelum peduli pada negara, kita terbiasa fokus pada lingkaran terdekat. Nah, konsep Kerja Sama Keluarga dalam Kelompok: Primer, Sekunder, Tersier, Kompleks ini menarik untuk dikaji. Ketika ikatan dalam kelompok primer dan sekunder sudah sangat kuat, seringkali energi kolektif habis di sana. Akibatnya, urusan politik yang berada di level kompleks terasa jauh, abstrak, dan akhirnya diabaikan karena dianggap tak langsung menyentuh dapur rumah tangga.
Pendidikan Politik dan Kepercayaan Diri Publik
Pendidikan kewarganegaraan di sekolah sering kali berhenti pada hafalan pasal-pasal dan teori demokrasi normatif, tanpa mengajarkan keterampilan kritis untuk menganalisis kekuasaan atau mekanisme advokasi yang konkret. Hasilnya, banyak lulusan sekolah yang memahami struktur pemerintahan tetapi tidak tahu cara meminta pertanggungjawaban darinya. Ini berkontribusi pada rasa tidak berdaya (low political efficacy) yang akut.
Kegagalan Pendidikan Formal dan Peran Masyarakat Sipil
Keyakinan bahwa satu suara tidak akan mengubah apa-apa adalah virus yang mematikan partisipasi. Ketika pendidikan formal gagal membangun keyakinan bahwa warga negara memiliki kekuatan, sikap apatis menjadi logis. Organisasi masyarakat sipil (CSO) seperti LSM, lembaga bantuan hukum, atau komunitas watchdog berusaha mengisi celah ini dengan pendidikan politik yang lebih aplikatif. Namun, jangkauan mereka sering terbatas pada kelompok tertentu, dan kadang dicurigai memiliki agenda tersendiri, sehingga tidak selalu berhasil membangun kepercayaan diri politik yang luas.
| Tingkat Pendidikan | Pemahaman tentang Mekanisme Politik | Minat terhadap Kegiatan Pemerintah | Kecenderungan Sikap |
|---|---|---|---|
| Rendah (SD/SMP) | Cenderung terbatas pada figur pemimpin, bukan sistem. Informasi banyak dari media tradisional/tunggal. | Sangat rendah, kecuali terkait bantuan sosial langsung. Politik dianggap abstrak. | Apatis pasif, karena merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk berkomentar. |
| Menengah (SMA/Sederajat) | Memahami struktur dasar, tetapi sering terjebak pada narasi populis dan polarisasi di media sosial. | Fluktuatif, bisa tinggi saat momentum tertentu (pemilu) tetapi cepat turun akibat kekecewaan. | Apatis sinis, merasa tahu sedikit tetapi percaya sistem sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki. |
| Tinggi (Perguruan Tinggi) | Memahami mekanisme yang lebih kompleks, mampu mengakses analisis yang beragam. | Bervariasi. Ada yang sangat kritis dan aktif, ada pula yang memilih fokus pada karir profesional dan menganggap politik tidak efisien. | Dualisme: antara partisipasi kritis dan apatis elit (disengagement karena merasa punya pilihan lain). |
Alternatif Saluran Pengaruh dan Ekspresi
Ketidakpedulian terhadap politik formal tidak selalu berarti pasif total. Banyak masyarakat, terutama generasi muda, justru menemukan saluran lain untuk menyuarakan aspirasi dan mempengaruhi perubahan, yang mereka anggap lebih efektif, langsung, dan otentik dibandingkan melalui partai politik atau lembaga legislatif. Mereka memilih jalur yang menghubungkan langsung antara aksi dan hasil yang mereka rasakan.
Gerakan Sosial Langsung dan Partisipasi Non-Konvensional
Ketika kepercayaan pada saluran representasi formal menipis, masyarakat beralih ke aksi langsung. Gerakan sosial berbasis isu spesifik, seperti lingkungan, kesetaraan gender, atau anti-korupsi, sering kali menarik lebih banyak minat karena jelas musuh dan tujuannya. Partisipasi non-konvensional seperti petisi online, donasi crowdfunding untuk kasus hukum, atau boikot terhadap produk perusahaan yang dianggap bermasalah, memberikan rasa kontrol dan dampak yang lebih terukur.
- Politik Formal: Memilih dalam pemilu, menghadiri musyawarah desa yang prosedural, menjadi anggota partai politik.
- Aktivitas Alternatif yang Dipilih: Menggalang dana untuk korban bencana secara mandiri, terlibat dalam komunitas bersih-bersih sungai, menyebarkan petisi daring untuk tolak proyek yang merusak lingkungan, memilih produk UMKM lokal sebagai bentuk dukungan ekonomi.
Bayangkan sebuah komunitas di pinggiran kota yang jalannya rusak parah. Selama bertahun-tahun mereka mengadukan ke pemerintah daerah melalui RT/RW dan surat resmi, tanpa hasil. Daripada terus menunggu, warga akhirnya mengumpulkan iuran sukarela, membeli material, dan bergotong-royong memperbaiki jalan tersebut dalam akhir pekan. Pilihan swadaya ini bukan sekadar tentang jalan, melainkan pernyataan politis yang tegas: “Kami bisa menyelesaikan masalah kami sendiri, tanpa bergantung pada sistem politik yang lamban dan tidak responsif.” Aksi nyata ini memberikan kepuasan dan hasil yang langsung terlihat, sesuatu yang jarang didapat dari kegiatan politik pemerintah.
Simpulan Akhir
Jadi, ketidakpedulian itu bukanlah vakum atau kehampaan, melainkan sebuah pilihan rasional dalam kerangka yang terbatas. Pilihan yang lahir dari kekecewaan berulang, informasi yang berantakan, dan keyakinan bahwa saluran lain—seperti gerakan komunitas atau ekspresi di media sosial—terasa lebih langsung dampaknya. Politik formal dianggap sebagai drama yang terlalu rumit untuk diikuti, sementara kehidupan nyata terus berdetak dengan ritmenya sendiri.
Pada akhirnya, membangun kembali kepedulian bukan sekadar menuntut masyarakat untuk lebih perhatian, tetapi menuntut sistem politik untuk lebih layak dipercaya, lebih transparan, dan lebih relevan dengan denyut nadi keseharian. Ketika politik mampu membuktikan dirinya bukan sebagai beban, melainkan sebagai alat pemecah masalah yang nyata, barulah ia akan kembali mendapat tempat di hati publik.
FAQ Terpadu
Apakah ketidakpedulian politik ini hanya terjadi di Indonesia?
Tidak, fenomena apatisme politik atau political disengagement terjadi di banyak negara, meski dengan pemicu dan bentuk yang berbeda-beda. Di Indonesia, konteks historis Orde Baru dan budaya tertentu memberikan warna yang khas.
Apakah media sosial justru memperparah ketidakpedulian ini?
Bisa jadi. Banjir informasi, hoaks, dan narasi negatif yang konstan di media sosial dapat menyebabkan kelelahan informasi (information overload) dan sinisme. Alih-alih memicu keterlibatan, banyak orang justru memilih untuk “menghindar” dari kebisingan tersebut.
Bagaimana dengan generasi muda yang melek teknologi, apakah mereka juga apatis?
Generasi muda mungkin tidak apatis terhadap isu-isu sosial. Namun, ketidakpedulian mereka seringkali tertuju pada politik formal dan partai politik. Mereka cenderung lebih aktif dalam bentuk partisipasi non-konvensional seperti petisi online, kampanye media sosial, atau gerakan isu spesifik yang dirasakan lebih autentik.
Apakah orang yang tidak peduli politik berarti tidak cinta negara?
Sama sekali tidak. Kecintaan pada negara bisa diekspresikan melalui banyak cara: dengan menjadi warga yang taat hukum, menjaga lingkungan, berkontribusi pada komunitas, atau bekerja keras. Mengaitkan patriotisme semata-mata dengan minat pada politik pemerintah adalah penyederhanaan yang keliru.
Lantas, apakah kondisi ini berbahaya bagi demokrasi?
Dalam jangka panjang, bisa ya. Demokrasi memerlukan partisipasi dan pengawasan dari warganya. Ketidakpedulian yang masif dapat membuat kebijakan hanya ditentukan oleh segelintir orang yang aktif, meningkatkan ruang bagi praktik koruptif, dan melemahkan akuntabilitas pemerintah.