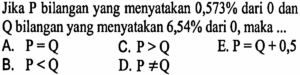Pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Qadariyah tentang Musibah dan Kezaliman itu ibarat dua lensa berbeda untuk memandangi realitas yang sama. Di satu sisi, ada ketenangan yang dalam dari penerimaan akan skenario ilahi, sementara di sisi lain, ada gelora semangat untuk mengubah takdir yang terlihat pahit. Topik ini bukan cuma debat teologis klasik yang berdebu, tapi tentang bagaimana kita, hari ini, menyikapi derita yang datang tiba-tiba atau ketidakadilan yang menganga.
Mari kita telusuri, karena jawabannya menentukan apakah kita lebih banyak mengeluh atau banyak bergerak.
Perbedaan mendasar kedua mazhab ini bersumber dari cara memandang kuasa mutlak Tuhan dan kebebasan memilih manusia. Ahlus Sunnah, dengan konsep qadha dan qadarnya, melihat segala peristiwa—entah itu gempa bumi atau penindasan—telah tercatat dalam ilmu Allah. Sementara Qadariyah menekankan bahwa manusia punya kekuasaan penuh atas perbuatannya, sehingga kezaliman adalah murni buah pilihan pelakunya, bukan takdir yang dipaksakan. Dari sini, lahirlah dua sikap hidup yang sangat kontras dalam menghadapi cobaan dan ketidakadilan di dunia.
Akar Metafisik Perbedaan Pandangan antara Takdir Ilahi dan Kebebasan Manusia
Perdebatan tentang musibah dan kezaliman dalam Islam seringkali bermuara pada satu persoalan mendasar: di mana batas kekuasaan Tuhan dan di mana ruang kebebasan manusia? Dua arus pemikiran utama, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Qadariyah, memberikan jawaban yang berbeda, yang kemudian membentuk cara pandang mereka terhadap penderitaan dan ketidakadilan di dunia.
Konsep Qadha dan Qadar dalam Perspektif Ahlus Sunnah
Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan pada qadha dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Qadar adalah ketetapan Allah yang azali, rencana-Nya yang terperinci untuk segala sesuatu di alam semesta, sejak sebelum penciptaan. Sementara qadha adalah perwujudan atau eksekusi dari ketetapan tersebut dalam realitas. Dalam kerangka ini, segala peristiwa, termasuk musibah alam dan kezaliman manusia, terjadi dengan ilmu, kehendak, dan kekuasaan Allah.
Namun, ini tidak menjadikan manusia sekadar wayang yang tak berdaya. Ahlus Sunnah meyakini bahwa manusia memiliki kehendak dan kemampuan (qudrah) yang diberikan oleh Allah, dan dengan itu ia memilih perbuatannya. Kezaliman yang dilakukan seseorang adalah pilihannya sendiri, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan itu, meskipun dalam skema besar, pilihan itu terjadi dalam koridor ilmu dan kehendak Allah. Musibah dilihat sebagai ujian, peringatan, atau bentuk kasih sayang yang tersembunyi, yang kesemuanya mengandung hikmah meski mungkin tak terjangkau akal manusia.
Doktrin Inti Qadariyah dan Implikasi Moralnya
Qadariyah, yang muncul di awal sejarah Islam, mengambil posisi yang berbeda. Mereka menekankan bahwa manusia adalah pencipta perbuatannya sendiri, baik yang baik maupun yang buruk. Tuhan memberikan manusia kebebasan (free will) dan kemampuan (istitha’ah) yang sepenuhnya independen sebelum sebuah perbuatan dilakukan. Dengan demikian, Tuhan tidak menciptakan kezaliman; yang menciptakannya adalah manusia yang zalim. Implikasi dari doktrin ini sangat jelas dalam penilaian moral: kezaliman adalah murni kesalahan dan tanggung jawab pelakunya, tanpa campur tangan takdir Ilahi.
Pandangan ini membawa semangat progresif untuk menentang ketidakadilan, karena tidak ada ruang untuk berkata, “Ini sudah takdir,” sebagai pembenaran. Setiap kejahatan harus dilawan karena ia bersumber dari kehendak manusia yang salah, bukan dari kehendak Tuhan yang harus pasrah diterima.
Perbandingan Konseptual antara Ahlus Sunnah dan Qadariyah, Pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Qadariyah tentang Musibah dan Kezaliman
Perbedaan mendasar antara kedua pandangan ini dapat dirangkum dalam beberapa aspek kunci berikut.
| Aspek | Ahlus Sunnah wal Jamaah | Qadariyah |
|---|---|---|
| Sifat Perbuatan | Diciptakan oleh Allah, diperoleh (kasb) oleh manusia dengan kehendak dan kemampuannya. | Diciptakan sepenuhnya oleh manusia. |
| Sumber Kekuasaan | Kekuasaan manusia (qudrah) adalah anugerah sekaligus ciptaan Allah yang muncul bersamaan dengan perbuatan. | Kemampuan manusia (istitha’ah) ada sebelum perbuatan dan bersifat mandiri. |
| Peran Kehendak Ilahi | Meliputi segala sesuatu, termasuk kehendak manusia untuk berbuat jahat, namun tanpa paksaan. | Hanya meliputi kebaikan. Kehendak Tuhan tidak menghendaki kezaliman. |
| Konsekuensi Teologis | Menjaga kemahakuasaan Tuhan secara mutlak, tetapi tetap menegaskan keadilan-Nya dalam menghisab manusia. | Menjaga keadilan Tuhan secara absolut dengan membebankan tanggung jawab penuh pada manusia, namun berisiko membatasi kemahakuasaan-Nya. |
Implikasi Praktis Doktrin Takdir pada Sikap Sosial dan Pola Pemberian Bantuan
Keyakinan teologis bukan hanya urusan abstrak; ia langsung mempengaruhi sikap dan tindakan nyata suatu komunitas. Cara seseorang memandang takdir akan sangat menentukan bagaimana ia merespons penderitaan orang lain, baik akibat gempa bumi maupun akibat penindasan sesama manusia.
Respons Komunitas Ahlus Sunnah terhadap Korban Musibah
Dalam komunitas Ahlus Sunnah, keyakinan pada takdir yang telah ditetapkan menciptakan sikap dasar: penerimaan (rida) dan kesabaran (sabar). Ketika musibah alam terjadi, respons pertama seringkali adalah introspeksi diri dan memperbanyak istighfar, melihat musibah sebagai teguran dari Allah. Sikap ini mendorong solidaritas yang dalam, karena membantu korban dipandang sebagai bagian dari ibadah dan bentuk kesabaran yang aktif. Bantuan diberikan dengan penuh empati, disertai nasihat untuk bersabar dan mengharap pahala.
Namun, dalam konteks kezaliman sosial, interpretasi takdir bisa menimbulkan dinamika kompleks. Di satu sisi, kezaliman dipandang sebagai perbuatan pelakunya yang akan dihisab. Di sisi lain, karena terjadi dalam koridor takdir Ilahi, bisa muncul sikap kurang tegas untuk mengubah struktur ketidakadilan, dengan anggapan bahwa perubahan hanya akan terjadi jika Allah menghendakinya. Fokus lebih banyak pada memperbaiki diri dan berdoa, sambil tetap membantu korban secara individual.
Dalam diskursus teologi Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang musibah dan kezaliman sebagai bagian dari takdir yang telah ditetapkan, sementara Qadariyah menekankan peran mutlak kebebasan manusia. Namun, memahami takdir juga butuh logika sistematis, mirip seperti saat kita Tentukan Tingkat Bunga dari Persamaan Permintaan Investasi I=500‑800i yang memerlukan analisis presisi. Pada akhirnya, refleksi atas rumus ekonomi itu mengingatkan kita bahwa, sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah, segala sesuatu berjalan di bawah ilmu dan ketentuan-Nya yang Maha Tahu.
Argumentasi Qadariyah untuk Aksi Sosial Progresif
Qadariyah membangun pola argumentasi yang berbeda. Bagi mereka, karena kezaliman adalah ciptaan manusia, maka kewajiban untuk menghilangkannya juga sepenuhnya berada di pundak manusia. Doa dan pasrah tanpa aksi nyata dianggap sebagai pengingkaran terhadap tanggung jawab yang telah Tuhan berikan. Tuhan telah memberikan akal, hukum sebab-akibat, dan kebebasan untuk mengubah keadaan. Musibah sosial seperti kemiskinan struktural atau tirani bukanlah “takdir” yang harus diterima, melainkan “masalah” yang harus dipecahkan melalui usaha kolektif.
Keyakinan ini mendorong etos kerja sosial yang sangat progresif dan menuntut perubahan sistemik.
Langkah-Langkah Advokasi Berbasis Prinsip Qadariyah
Pendekatan advokasi yang lahir dari prinsip Qadariyah akan sangat menekankan agency (kemampuan bertindak) manusia. Berbeda dengan pendekatan fatalis yang mungkin hanya berfokus pada bantuan karitatif, advokasi model Qadariyah akan bersifat transformatif.
- Penyadaran Akar Masalah: Mengedukasi masyarakat bahwa kezaliman bukanlah ketetapan Tuhan, melainkan hasil dari pilihan dan sistem yang dibuat manusia, sehingga bisa dan harus diubah.
- Pemberdayaan sebagai Kewajiban: Membangun kapasitas korban dan masyarakat luas untuk melawan ketidakadilan, karena mereka memiliki kemampuan (istitha’ah) yang diberikan Tuhan untuk itu.
- Advokasi Kebijakan Proaktif: Tidak hanya menunggu perubahan dari atas, tetapi aktif merancang dan memperjuangkan kebijakan yang adil, dengan keyakinan bahwa usaha manusia adalah bagian dari hukum alam yang Tuhan tetapkan.
- Penegasan Tanggung Jawab Pelaku: Menolak narasi yang membebaskan pelaku kezaliman dengan alasan “takdir”, dan menuntut pertanggungjawaban mereka di ranah hukum dan sosial.
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS Ar-Ra’d: 11) – Ayat ini sering menjadi rujukan utama Qadariyah untuk menegaskan tanggung jawab manusia.
“Bersabarlah, karena sesungguhnya kesabaran itu adalah sebuah kebajikan yang besar.” – Pesan ini lebih dominan dalam narasi Sunni ketika menghadapi musibah, menekankan penerimaan dan ketabahan hati.
Narasi Penderitaan dalam Literatur Keagamaan Sebagai Cermin Perdebatan Keadilan Ilahi
Kisah-kisah dalam Al-Qur’an dan sejarah Islam menjadi medan penafsiran yang hidup bagi kedua mazhab. Dari cerita Nabi Ayyub yang sakit parah hingga tragedi Karbala, cara menceritakan kembali peristiwa itu mengungkap perbedaan mendasar dalam memandang keadilan Tuhan dan peran manusia.
Penafsiran Kisah Nabi dan Umat Terdahulu
Ahlus Sunnah menafsirkan kisah penderitaan para nabi, seperti Nabi Ayyub, sebagai contoh sempurna dari kesabaran (sabar) dalam menerima takdir Allah yang terasa pahit. Musibah yang menimpa mereka adalah ujian tingkat tinggi untuk mengangkat derajat mereka, sekaligus demonstrasi bahwa cobaan berat bisa menimpa orang-orang terpilih. Bencana yang menimpa umat terdahulu, seperti kaum Nabi Nuh atau Luth, dilihat sebagai bentuk keadilan Ilahi (al-‘adl al-ilahi) yang sempurna, di mana hukuman itu adalah konsekuensi dari keingkaran mereka, namun tetap dalam rencana dan ilmu Allah.
Sementara Qadariyah akan menekankan sisi lain dari kisah yang sama. Penderitaan Nabi Ayyub bukanlah soal pasrah semata, tetapi tentang usahanya yang gigih untuk berdoa dan berobat, yang merupakan perwujudan dari kekuasaannya untuk berusaha dalam kerangka hukum alam Tuhan. Kehancuran suatu kaum lebih ditekankan sebagai akibat logis dan langsung dari pilihan kolektif mereka yang zalim, sebuah konsekuensi yang sepenuhnya berasal dari tindakan mereka sendiri, bukan sebuah “hukuman yang dijatuhkan” secara langsung oleh Tuhan di luar sebab-akibat.
Perbedaan Penekanan dalam Satu Peristiwa Sejarah
Ambil contoh Perang Uhud, di mana kaum Muslimin mengalami kekalahan pahit akibat kesalahan sebagian pasukan pemanah. Narasi Sunni akan menceritakannya dengan penekanan pada aspek takdir: kekalahan itu terjadi dengan izin Allah sebagai ujian dan pelajaran, serta sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Narasi ini tidak mengabaikan kesalahan manusia, tetapi memasukkannya ke dalam skenario Ilahi yang lebih besar. Sebaliknya, penekanan Qadariyah akan sepenuhnya pada kesalahan manusia itu sendiri.
Kekalahan adalah akibat langsung dan murni dari ketidakdisiplinan pasukan pemanah yang melangar perintah Nabi. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa hasil (kekalahan/kemenangan) sangat bergantung pada pilihan dan tindakan manusia, dan Tuhan membiarkan hukum sebab-akibat itu berlaku. Tuhan adil dengan memberikan konsekuensi yang sesuai atas pilihan yang diambil.
Ilustrasi Konseptual Pertarungan Qudrah dan Istitha’ah
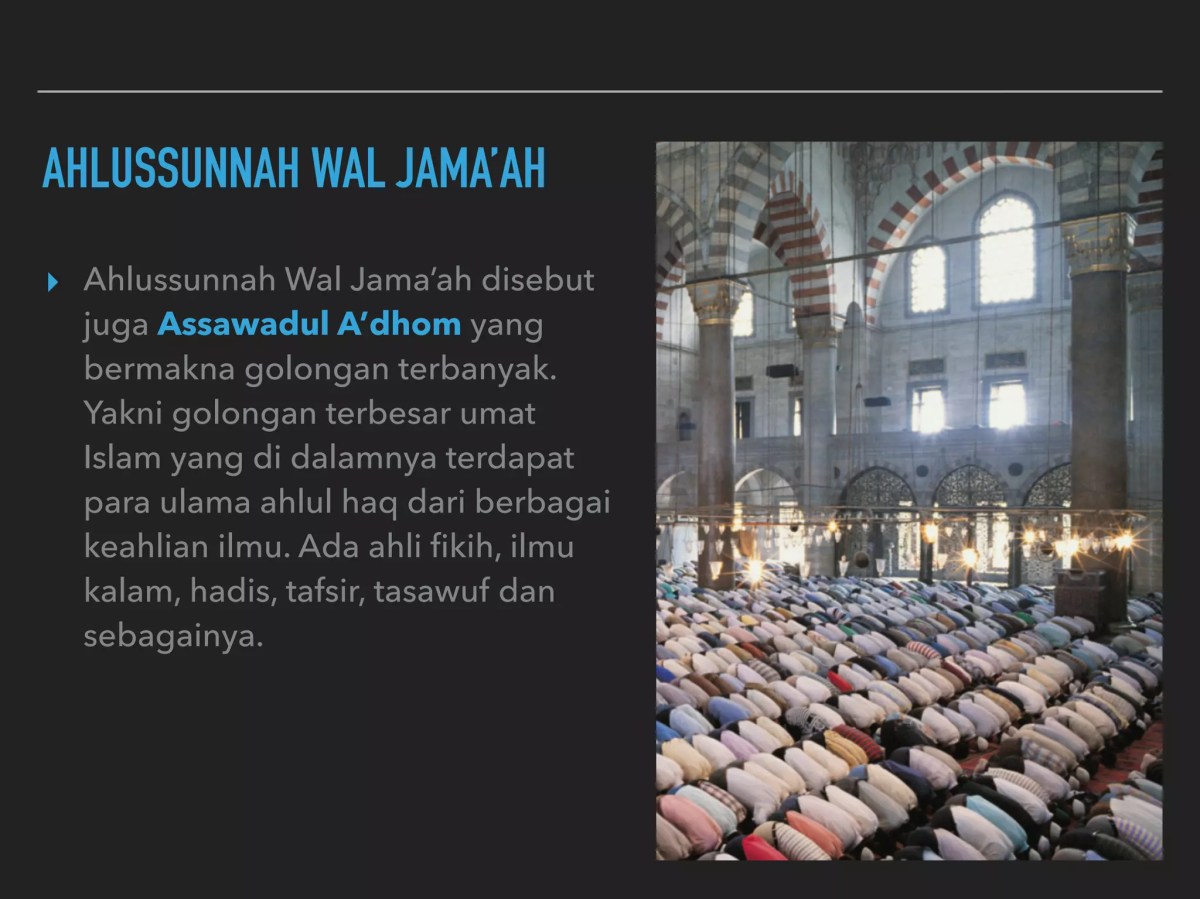
Source: slidesharecdn.com
Bayangkan sebuah lukisan alegori yang terbagi dua. Di sisi kiri, latar belakangnya adalah hamparan langit malam bertabur bintang yang membentuk pola kaligrafi “Kun Fayakun” (Jadilah, maka jadilah). Di tengah, seorang manusia berdiri dengan kedua tangannya terangkat, namun dari telapak tangannya memancar cahaya yang membentuk sebuah perbuatan—misalnya, sebilah pedang atau sebuah pena. Cahaya itu menyatu dengan pola bintang di langit, seolah-olah berasal dari sana dan sekaligus menjadi bagian darinya.
Ini melambangkan pandangan Sunni: perbuatan manusia (cahaya) diciptakan oleh Allah (pola bintang), dan manusia memperolehnya. Di sisi kanan lukisan, latarnya adalah kanvas kosong berwarna terang. Seorang manusia berdiri tegap, dan dari tangannya yang sama memancar cahaya yang menciptakan bentuk-bentuk baru secara mandiri di atas kanvas kosong itu—sebuah bangunan, pohon, atau alat. Cahaya itu murni dari dirinya, meski tubuhnya sendiri berada dalam siluet yang mengingatkan pada ciptaan Tuhan.
Di kejauhan, hanya ada cahaya Ilahi yang menerangi panggung, tetapi tidak membentuk pola. Ini melambangkan pandangan Qadariyah: manusia mencipta perbuatannya di atas “kanvas” kebebasan yang diberikan Tuhan. Sebuah garis samar membelah dua bagian lukisan ini, namun sosok manusia di kedua sisi saling memandang, mencerminkan dialektika abadi dalam pemikiran Islam.
Dialektika antara Doa, Ikhtiar, dan Konsekuensi yang Tak Terelakkan
Dalam kehidupan sehari-hari, ketegangan antara takdir dan usaha muncul dalam bentuk yang sangat konkret: haruskah kita berdoa dan berusaha keras, atau pasrah menerima apa pun hasilnya? Kedua mazhab menjawab pertanyaan ini dengan logika teologis mereka masing-masing.
Posisi Doa dan Usaha dalam Kerangka Takdir Sunni
Bagi Ahlus Sunnah, doa dan ikhtiar bukanlah hal yang kontradiktif dengan takdir, melainkan justru bagian dari takdir itu sendiri. Mereka menggunakan analogi seorang petani: takdir bahwa ia akan panen tidak berarti ia hanya duduk menunggu di rumah. Takdir itu justru mencakup usahanya membajak, menanam, dan merawat. Demikian pula, doa adalah sebab yang diperintahkan Allah untuk mencapai suatu hasil. Keyakinan bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan justru seharusnya mendorong seseorang untuk lebih giat berusaha dan berdoa, karena usaha dan doanya itu sendiri adalah jalan yang telah Allah tetapkan untuk mencapai takdir-Nya.
Hasil akhir, apakah sesuai harapan atau tidak, diterima dengan lapang dada karena itu adalah ketetapan yang terbaik menurut ilmu Allah, meski mungkin tidak sesuai dengan keinginan pribadi.
Pandangan Qadariyah tentang Doa dalam Sistem Sebab-Akibat
Qadariyah memandang doa sebagai salah satu sebab yang paling kuat dalam hukum sebab-akibat yang telah Tuhan tetapkan di alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dengan sistem yang konsisten, di mana doa memiliki “daya sebab” tertentu untuk mengubah keadaan. Doa bukanlah permohonan untuk mengintervensi takdir yang sudah “tercetak”, melainkan bagian aktif dari mekanisme perubahan itu sendiri. Dengan berdoa, manusia mengaktifkan satu sebab yang dapat membawa akibat yang diinginkan.
Kegagalan doa “terkabul” bukan karena sudah ditakdirkan gagal, tetapi bisa jadi karena tidak terpenuhinya sebab-sebab lain yang diperlukan, atau karena ada hikmah lain yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang tidak menghendaki kezaliman. Dalam pandangan ini, ikhtiar manusia—termasuk doa—memiliki peran yang sangat sentral dan determinatif dalam membentuk realitas kehidupannya.
Respons dalam Skenario Kehidupan Nyata
| Skenario | Respons Khas Ahlus Sunnah | Respons Khas Qadariyah |
|---|---|---|
| Sakit Penyakit | Berobat dengan sungguh-sungguh (ikhtiar jasmani), berdoa meminta kesembuhan, dan bersabar menerima apapun hasilnya. Sakit adalah ujian atau penghapus dosa yang telah ditakdirkan. | Berobat dan berdoa dengan keyakinan bahwa kedua usaha ini adalah sebab yang Allah tetapkan untuk kesembuhan. Penyakit adalah gangguan pada sistem tubuh yang harus dilawan. |
| Usaha Bisnis Gagal | Mengevaluasi kesalahan teknis, tetapi juga introspeksi diri. Percaya bahwa rezeki sudah ditakdirkan, dan kegagalan ini mungkin mengandung hikmah untuk hal yang lebih baik di masa depan. | Menganalisis kegagalan secara mendalam pada faktor manajemen, pasar, atau strategi. Percaya bahwa kesuksesan adalah hasil dari merangkai sebab-sebab (kerja keras, ilmu, jaringan) dengan benar. |
| Konflik Keluarga | Berusaha mendamaikan dengan baik, banyak berdoa untuk dilunakkan hati, dan bersabar menghadapi sifat pasangan/keluarga yang mungkin sudah menjadi takdirnya. | Aktif mencari solusi komunikasi, mediasi, atau psikologis. Percaya bahwa hubungan yang baik dibangun melalui usaha dan keterampilan sosial, bukan hanya ditakdirkan saja. |
| Bencana Alam | Membantu korban sebagai ibadah, menguatkan dengan nasihat sabar, dan melihat bencana sebagai peringatan dari Allah atas dosa-dosa kolektif. | Membantu korban dan simultan mengkritik lemahnya sistem mitigasi, tata kota, atau early warning. Bencana adalah peristiwa alam yang risikonya harus diminimalisir oleh akal manusia. |
Rekonsiliasi Semu dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik
Pertentangan antara paham jabariyah (fatalis) dan qadariyah (free will) yang ekstrem selalu dianggap berbahaya bagi akidah dan keutuhan umat. Karena itu, sepanjang sejarah, para ulama besar berusaha mencari jalan tengah atau minimal meredakan ketegangan dengan argumen-argumen yang menjaga keseimbangan.
Upaya Historis Para Tokoh Pemersatu
Imam Al-Ghazali, dalam karya-karyanya, berusaha mensintesiskan kemahakuasaan Tuhan dengan keadilan-Nya. Ia membedakan antara kehendak Tuhan (iradah) yang bersifat universal dan meliputi segala hal, dengan ridha Tuhan yang hanya untuk kebaikan. Artinya, kezaliman terjadi dengan kehendak-Nya tetapi tidak dengan ridha-Nya. Ini adalah upaya untuk menjaga kedua belah pihak: Tuhan tetap berkuasa mutlak, tetapi tidak “bertanggung jawab” atas kejahatan. Sementara Ibnu Taimiyah lebih menekankan pada penyelesaian praktis.
Ia mengkritik baik kelompok fatalis yang malas beramal maupun kelompok qadariyah yang sombong dengan usahanya. Baginya, seorang Muslim harus meyakini takdir sekaligus berusaha maksimal, seperti perintah dalam hadis: “Berusahalah, karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang telah ditakdirkan untuknya.” Upaya-upaya ini bukan rekonsiliasi penuh, melainkan lebih pada penempatan persoalan pada proporsinya agar tidak merusak sendi-sendi keyakinan dasar dan kohesi sosial.
Argumen untuk Meredam Ketegangan dan Menjaga Kohesi
Para ulama peredam ini biasanya menggunakan beberapa argumen kunci. Pertama, argumen bahwa persoalan ini termasuk perkara ghaib yang tidak bisa dijangkau sepenuhnya oleh akal manusia, sehingga berdebat tanpa ujung adalah sia-sia. Kedua, menekankan bahwa kedua belah pihak sebenarnya sepakat pada konsekuensi praktis: manusia wajib beramal shaleh dan akan dihisab atas perbuatannya. Ketiga, mengingatkan bahwa perdebatan sengit tentang takdir pada masa awal Islam seringkali dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan, sehingga umat harus kembali kepada nash yang jelas dan meninggalkan spekulasi yang berlebihan.
Dengan cara ini, mereka berusaha menjaga umat dari perpecahan dengan menyepakati hal-hal praktis dan mengesampingkan perbedaan metafisik yang rumit.
“Iman kepada takdir adalah tiang keyakinan, dan mengingkarinya adalah penghancur agama. Namun, berdebat tentangnya adalah bid’ah… Cukuplah bagimu mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan meleset darimu, dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah kamu peroleh.” – Pernyataan semacam ini sering ditemukan dalam nasihat ulama klasik, menekankan penerimaan praktis tanpa terjebak dalam debat kusir.
Ringkasan Penutup: Pandangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dan Qadariyah Tentang Musibah Dan Kezaliman
Jadi, setelah menyelami kedua pandangan ini, kita seperti diajak untuk berdiri di persimpangan yang sangat manusiawi. Di satu jalan, ada kedamaian hati karena percaya bahwa di balik semua musibah ada hikmah dan rencana ilahi yang tak terjangkau akal. Di jalan lain, ada api tanggung jawab yang menyala-nyala, mendorong untuk berbuat dan memperbaiki, karena kezaliman bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja.
Perdebatan klasik antara takdir dan ikhtiar ini ternyata masih sangat relevan, lho, untuk membaca berita duka atau melihat ketimpangan sosial di timeline kita.
Pada akhirnya, mungkin kebijaksanaan terbesar justru terletak pada kemampuan untuk tidak terjebak secara mutlak pada salah satu kutub. Seperti upaya rekonsiliasi para ulama klasik, memahami bahwa kuasa Allah itu mutlak, tetapi Dia juga yang menganugerahkan kehendak dan kemampuan kepada manusia. Sehingga, sikap pasrah yang tawakal tidak serta-merta membunuh semangat untuk berikhtiar. Dan, perjuangan memberantas kezaliman tidak harus berarti mengingkari takdir.
Ibaratnya, kita berlayar dengan memperhitungkan angin dan arus (takdir), tetapi tetap memegang kemudi (ikhtiar) sebaik-baiknya menuju pantai yang dituju.
Pertanyaan Populer dan Jawabannya
Apakah paham Qadariyah sama dengan paham Mu’tazilah?
Tidak sepenuhnya sama, tetapi sangat berhubungan erat. Qadariyah adalah istilah awal untuk kelompok yang menekankan kebebasan dan kekuasaan manusia atas perbuatannya. Sementara Mu’tazilah adalah mazhab teologi sistematis yang kemudian mengadopsi dan mengembangkan doktrin keadilan Tuhan (al-‘adl) yang salah satu konsekuensinya adalah penolakan terhadap paksaan takdir (jabr), sehingga mereka juga sering disebut sebagai Qadariyah. Namun, Mu’tazilah memiliki lima prinsip utama (al-usul al-khamsah), bukan hanya tentang qadar.
Bagaimana cara sederhana membedakan pandangan Sunni dan Qadari dalam melihat kecelakaan?
Bayangkan ada kecelakaan mobil. Pandangan Sunni akan melihatnya sebagai takdir yang telah tertulis, di mana pertemuan antara pengemudi A dan B di titik itu, kondisi kendaraan, dan hasil tabrakan sudah dalam ilmu Allah. Hikmahnya mungkin untuk mengangkat derajat si korban atau sebagai peringatan. Pandangan Qadariyah akan lebih menitikberatkan pada penyebab manusiawinya: apakah pengemudi ugal-ugalan, lalai, atau melanggar rambu? Sehingga, solusinya adalah penegakan aturan lalu lintas yang lebih ketat dan kampanye keselamatan berkendara.
Apakah percaya pada takdir membuat seorang Sunni tidak boleh marah pada kezaliman?
Tidak. Percaya pada takdir tidak berarti menerima kezaliman secara pasif. Marah terhadap kemungkaran adalah bagian dari iman. Perbedaan terletak pada kerangka berpikirnya. Seorang Sunni akan melawan kezaliman karena itu adalah perintah agama untuk amar ma’ruf nahi munkar, sekaligus meyakini bahwa hasil akhir dari perjuangannya (berhasil atau tidak) sudah tercatat dalam takdir.
Jadi, ia berjuang semaksimal mungkin, lalu menerima hasilnya dengan lapang dada karena itu adalah ketetapan Allah yang terbaik menurut-Nya.
Dari mana asal usul nama “Qadariyah”? Apakah dari kata “Qadar” (takdir)?
Ini adalah poin yang sering membingungkan. Nama “Qadariyah” justru diberikan oleh lawan-lawan polemis mereka (kaum Jabariyah/Sunni), dan konon bermakna celaan. Istilah ini diambil dari kata “qadar”, tetapi maksudnya adalah bahwa kelompok ini “mengaku-aku” memiliki “qadar” (kekuasaan/ kemampuan) atas perbuatan mereka sendiri, yang dianggap menyamai kekuasaan Tuhan. Jadi, penamaan ini bersifat satire. Kelompok ini sendiri mungkin lebih suka menyebut diri sebagai “Ahlu al-‘Adl wa al-Tauhid” (penganut keadilan dan keesaan Tuhan).
Manakah pandangan yang lebih dominan di dunia Islam saat ini?
Pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah (dalam hal ini Asy’ariyah dan Maturidiyah) adalah pandangan yang dipegang oleh mayoritas umat Islam di dunia, dari Asia hingga Afrika. Pandangan Qadariyah dalam bentuk murni historisnya sudah tidak ada sebagai mazhab terorganisir, namun semangat dan penekanannya pada tanggung jawab manusia, keadilan, dan perlawanan terhadap kezaliman tetap hidup dan berpengaruh dalam pemikiran dan gerakan Islam modern serta kontemporer yang menekankan perubahan sosial.