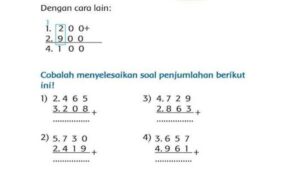Nilai kebersamaan dari penyelesaian kontroversi Jakarta Charter bukan sekadar catatan sejarah yang usang, melainkan sebuah mahakarya diplomasi jiwa bangsa yang masih terasa hangat hingga kini. Bayangkan ruang sidang yang tegang di tahun 1945, di mana tujuh kata yang sarat makna—”dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”—hampir saja menjadi garis pemisah di tengah upaya merajut kesatuan. Perdebatan sengit itu justru menjadi panggung tempat semangat gotong royong dan kecerdasan kolektif para pendiri bangsa diuji.
Mengupas peristiwa ini lebih dalam, kita akan menemukan sebuah narasi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar kompromi politik biasa. Ini adalah kisah tentang bagaimana tokoh-tokoh dari latar belakang yang berbeda duduk bersama, mendengarkan, dan pada akhirnya mengutamakan tanah air di atas segalanya. Pergulatan antara aspirasi keagamaan yang kuat dan visi negara bangsa yang inklusif akhirnya melahirkan rumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang kita kenal sekarang, sebuah fondasi yang dibangun bukan dari kemenangan satu kelompok, tetapi dari kearifan bersama.
Konteks Historis dan Makna Piagam Jakarta
Sebelum Indonesia merdeka, para pendiri bangsa sudah sibuk merancang dasarnya. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengadakan sidang pada pertengahan 1945, dan di sanalah konsep dasar negara diperdebatkan dengan sangat serius. Dalam suasana yang penuh semangat namun juga tegang, lahirlah sebuah dokumen penting yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Dokumen ini sebenarnya adalah rancangan pembukaan undang-undang dasar, yang memuat lima sila Pancasila dalam rumusan awalnya, plus satu klausul yang kemudian menjadi sumber perdebatan panjang.
Inti dari kontroversi itu terletak pada tujuh kata dalam klausul tentang keagamaan. Piagam Jakarta, yang disepakati pada 22 Juni 1945, mencantumkan kalimat: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Klausul inilah yang menjadi titik panas. Bagi sebagian besar tokoh dari kalangan Islam, ini adalah bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap mayoritas penduduk. Sementara bagi tokoh dari Indonesia Timur dan kalangan yang menginginkan negara bersifat lebih inklusif, tujuh kata itu dirasakan dapat mengancam kesatuan bangsa yang baru akan lahir.
Perbandingan Rumusan Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945
Perubahan dari Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD 1945 adalah sebuah kompromi politik yang brilian dan penuh ketegangan. Untuk melihat perbedaannya secara jelas, berikut adalah tabel yang membandingkan kedua naskah tersebut, khususnya pada bagian yang paling krusial.
| Aspek | Piagam Jakarta (22 Juni 1945) | Pembukaan UUD 1945 (18 Agustus 1945) | Catatan Perubahan |
|---|---|---|---|
| Status Dokumen | Rancangan Pembukaan (Preambule) UUD | Pembukaan (Preambule) UUD 1945 yang sah dan tetap | Disahkan sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. |
| Klausul Keagamaan | “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” | “Ketuhanan Yang Maha Esa” | Tujuh kata dihilangkan. Rumusan menjadi lebih universal dan mencakup semua agama. |
| Sila Pertama Pancasila | Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya | Ketuhanan Yang Maha Esa | Menjadi dasar negara yang netral secara agama namun berke-Tuhan-an. |
| Dampak Konsekuensi Hukum | Berpotensi memberlakukan hukum syariat bagi umat Islam secara konstitusional. | Tidak ada kewajiban konstitusional yang spesifik terhadap satu agama. | Mencegah pembelahan masyarakat berdasarkan hukum agama dan menjamin kesetaraan warga negara. |
Dinamika dan Proses Penyelesaian Kontroversi
Setelah Piagam Jakarta disepakati, ternyata perjalanannya belum selesai. Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 justru mempertajam kebutuhan akan kesepakatan final. Berita tentang tujuh kata itu sampai juga ke berbagai daerah, terutama Indonesia Timur, dan menimbulkan kekhawatiran serius. Inilah yang memicu sebuah proses negosiasi yang sangat intens dalam waktu yang sangat singkat, melibatkan tokoh-tokoh kunci dengan latar belakang yang berbeda.
Aktor-aktor utama dalam drama politik ini antara lain Mohammad Hatta sebagai wakil presiden, Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mohammad Hasan dari Sumatra. Tokoh-tokoh dari kalangan Islam seperti Ki Bagus pada awalnya berpegang teguh pada Piagam Jakarta sebagai hasil kesepakatan. Namun, mereka juga dihadapkan pada realitas bahwa dukungan dari seluruh Nusantara, termasuk dari Kristen dan masyarakat adat di Timur, sangat krusial bagi kelangsungan Republik yang masih bayi.
Alur Kronologis Peristiwa Penting

Source: googleapis.com
Rangkaian peristiwa dari perumusan hingga perubahan klausul kontroversial terjadi dalam tempo yang sangat cepat, mencerminkan dinamika politik yang tinggi di masa revolusi.
- 22 Juni 1945: Piagam Jakarta disepakati oleh Panitia Sembilan BPUPKI sebagai kompromi antara kalangan Islam dan kebangsaan.
- 17 Agustus 1945: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan. Piagam Jakarta masih tercantum sebagai pembukaan rancangan UUD.
- 18 Agustus 1945 pagi: Mohammad Hatta menerima informasi dari perwira Jepang (Nishimura) dan tokoh dari Indonesia Timur (disebutkan A.A. Maramis menemui Kasman) tentang penolakan terhadap tujuh kata. Kekhawatiran akan pecahnya negara disampaikan.
- 18 Agustus 1945 sebelum sidang PPKI: Hatta mengadakan pertemuan darurat dengan tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Wahid Hasyim, dan Teuku Moh Hasan. Dialog dan negosiasi alot terjadi.
- 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI: Atas usul Hatta, dengan dukungan dari tokoh-tokoh Islam yang telah menyetujui perubahan, klausul tujuh kata dihapus dan diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sidang menerima perubahan tersebut.
Argumen yang Berkembang dari Berbagai Pihak
Perdebatan tidak hanya terjadi di ruang sidang, tetapi juga dalam lobi-lobi politik. Di satu sisi, kelompok yang ingin mempertahankan tujuh kata berargumen bahwa hal itu adalah bentuk pengakuan historis dan keadilan bagi mayoritas Muslim yang telah berjuang. Mereka melihatnya sebagai wujud dari “kata hati” rakyat Indonesia. Di sisi lain, kelompok yang menolak, yang diwakili oleh tokoh dari Indonesia Timur dan Kristen, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara untuk semua suku dan agama.
Mereka berargumen bahwa pencantuman syariat Islam akan membuat mereka merasa menjadi warga negara kelas dua dan berpotensi memicu disintegrasi sejak hari pertama kemerdekaan.
Nilai Kebersamaan dan Semangat Gotong Royong dalam Penyelesaian: Nilai Kebersamaan Dari Penyelesaian Kontroversi Jakarta Charter
Di balik perubahan tujuh kata itu, tersimpan nilai luhur yang sering kita sebut-sebut tetapi mungkin lupa akar sejarahnya: gotong royong. Peristiwa 18 Agustus 1945 adalah contoh nyata bagaimana musyawarah untuk mufakat dan kesediaan berkorban untuk kepentingan yang lebih besar benar-benar dipraktikkan dalam keadaan yang sangat genting. Ini bukan sekadar kompromi politik biasa, melainkan sebuah konsensus nasional yang dilandasi oleh kesadaran bahwa persatuan adalah harga mati.
Bentuk kompromi yang paling gamblang adalah kesediaan tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo untuk melepas sesuatu yang sangat mereka perjuangkan. Mereka mengesampingkan tuntutan kelompoknya demi menjaga agar Republik Indonesia yang baru lahir tidak langsung terpecah belah. Di sisi lain, pengakuan terhadap “Ketuhanan Yang Maha Esa” juga merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai religius yang hidup dalam masyarakat. Jadi, yang terjadi adalah pertukaran pengorbanan, bukan kemenangan satu pihak atas pihak lain.
Dialog Tokoh yang Merefleksikan Semangat Kebersamaan
Percakapan dan pernyataan dalam pertemuan darurat pagi itu menggambarkan betapa beratnya keputusan yang diambil, namun juga menunjukkan kebesaran jiwa para pendiri bangsa.
“Sebagai seorang Muslim dan anggota PPKI, saya ikhlas tujuh kata itu dihapuskan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih baik mengganti tujuh kata itu daripada melihat Indonesia Timur memisahkan diri.”
Pernyataan di atas, yang disampaikan oleh salah satu tokoh kunci dari kalangan Islam, mencerminkan semangat pengorbanan yang luar biasa. Mereka memilih untuk “mengalah” bukan karena lemah, tetapi karena memiliki visi yang jauh lebih besar tentang sebuah bangsa yang utuh dan berdaulat. Inilah esensi dari kebersamaan: kemampuan untuk melihat diri sendiri sebagai bagian dari suatu keseluruhan yang lebih penting.
Implikasi Sosial dan Keindonesiaan dari Hasil Kompromi
Keputusan untuk menghapus tujuh kata dari Piagam Jakarta memiliki dampak yang langsung dan mendalam. Secara praktis, keputusan itu meredakan ketegangan yang sudah mulai memanas, khususnya di Indonesia Timur. Republik yang baru lahir bisa menarik napas lega dan mulai berkonsentrasi pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda. Secara konseptual, kompromi ini menjadi fondasi dari Indonesia yang inklusif, di mana identitas keagamaan tidak menjadi syarat untuk menjadi warga negara sepenuhnya.
Dari sinilah konsep Bhinneka Tunggal Ika mendapatkan bentuk konstitusionalnya yang pertama. Negara tidak berdiri atas dasar satu agama tertentu, tetapi atas dasar kesepakatan bersama untuk hidup dalam satu kesatuan politik. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa kemudian diterjemahkan sebagai keyakinan bahwa negara mengakui dan melindungi semua agama yang ada, tanpa menempatkan satu di atas yang lain secara hukum. Ini adalah konsep keindonesiaan yang unik, hasil dari pergumulan pemikiran yang matang di tengah tekanan waktu yang sangat singkat.
Analisis Skenario: Andai Kompromi Tidak Tercapai
Membayangkan apa yang akan terjadi jika tujuh kata itu tetap bertahan bukanlah hal yang mustahil. Dengan melihat konflik-konflik berbasis identitas di berbagai belahan dunia, kita bisa memperkirakan beberapa skenario yang mungkin terjadi.
| Aspek Dampak | Skenario Kompromi Tercapai | Skenario Kompromi Gagal | Pelajaran yang Diambil |
|---|---|---|---|
| Integrasi Nasional | Republik berhasil menarik dukungan luas dari seluruh wilayah, dari Aceh hingga Papua, untuk melawan Belanda. | Potensi kuat terjadinya disintegrasi sejak awal, dengan daerah-daerah non-Muslim (terutama Timur) menolak bergabung atau membentuk negara sendiri. | Persatuan dalam keberagaman adalah prasyarat mutlak bagi kelangsungan hidup sebuah negara bangsa yang majemuk. |
| Hubungan Antarumat Beragama | Dasar negara yang netral menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih setara, meski ketegangan sosial tetap mungkin terjadi. | Konstitusi secara legal membedakan warga berdasarkan agama, berpotensi memicu diskriminasi struktural dan konflik horizontal yang berkepanjangan. | Hukum dasar negara harus menjadi payung bagi semua warga, bukan alat untuk mengistimewakan satu kelompok. |
| Pembangunan Demokrasi | Terbuka peluang untuk membangun demokrasi yang, meskipun berliku, berlandaskan kesetaraan warga negara di depan hukum. | Demokrasi akan terdistorsi oleh politik identitas yang sangat kental, dengan kompetisi politik berdasarkan agama daripada program. | Kompromi politik yang inklusif di saat fondasi negara diletakkan akan menentukan corak politik suatu bangsa untuk puluhan tahun ke depan. |
| Citra Indonesia di Dunia | Indonesia dipandang sebagai contoh negara Muslim moderat dan demokratis yang berhasil memadukan Islam, demokrasi, dan modernitas. | Indonesia mungkin akan lebih cepat dikenal sebagai negara yang berdasarkan hukum agama tertentu, dengan segala kompleksitas dan tantangan eksternalnya. | Pilihan di masa lalu membentuk narasi dan identitas bangsa di kancah internasional. |
Refleksi Nilai dalam Konteks Kekinian
Nilai kebersamaan dan gotong royong yang ditunjukkan para pendiri bangsa dalam menyelesaikan kontroversi Piagam Jakarta bukanlah sekadar cerita sejarah yang usang. Di era sekarang, di mana perbedaan pendapat mudah sekali mengeras menjadi polarisasi dan perpecahan, semangat itu justru lebih relevan daripada sebelumnya. Tantangan menjaga persatuan kini tidak lagi datang dari ancaman pemisahan diri secara fisik, tetapi dari retaknya kohesi sosial akibat hoaks, ujaran kebencian, dan politik identitas yang sempit.
Kita hidup di zaman di mana ego sektoral—baik atas nama agama, suku, atau kepentingan kelompok—seringkali dianggap lebih penting daripada kepentingan bangsa secara keseluruhan. Di sinilah kita perlu kembali belajar dari musyawarah alot pagi itu: bahwa keberanian untuk mendengar pihak lain dan kesediaan untuk mengalah sementara untuk kemenangan bersama adalah kekuatan, bukan kelemahan.
Prinsip Penyelesaian yang Masih Relevan
Beberapa prinsip yang bisa kita petik dari peristiwa bersejarah tersebut dan masih sangat aplikatif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat publik saat ini antara lain:
- Prioritaskan Kepentingan Bersama yang Lebih Besar: Para tokoh meletakkan kelangsungan hidup Republik di atas kepentingan golongan atau ideologi pribadi.
- Komunikasi Intensif dan Dialog Langsung: Penyelesaian ditempuh melalui pertemuan tatap muka dan pembicaraan dari hati ke hati, bukan melalui cuitan atau status media sosial yang penuh emosi.
- Mencari Titik Temu, Bukan Kemenangan Mutlak: Hasil akhirnya adalah rumusan baru (“Ketuhanan Yang Maha Esa”) yang bisa diterima semua pihak, meski tidak sepenuhnya memuaskan salah satu pihak.
- Kecepatan dan Ketepatan Waktu: Mereka bertindak cepat dalam waktu kurang dari 24 jam untuk mencegah krisis yang lebih besar, menunjukkan kesigapan dalam mengambil keputusan strategis.
- Kepemimpinan yang Melayani Konsensus: Tokoh seperti Hatta bertindak sebagai fasilitator yang mendengarkan semua suara dan mengarahkan pada solusi, bukan sebagai pemimpin yang memaksakan kehendak.
Ilustrasi Deskriptif Semangat Sidang, Nilai kebersamaan dari penyelesaian kontroversi Jakarta Charter
Bayangkan sebuah ruangan yang tidak terlalu luas di Gedung Pejambon, Jakarta, pada pagi hari 18 Agustus 1945. Udara terasa berat, lebih berat dari biasanya. Di sekitar meja, duduk beberapa pria dengan raut wajah yang serius dan sedikit letih. Mohammad Hatta, dengan kacamata bulatnya, duduk tegak namun matanya menunjukkan beban yang ia pikul. Di hadapannya, Ki Bagus Hadikusumo duduk dengan tenang, tangan terkadang memegang janggutnya yang tipis, menandakan ia sedang berpikir sangat dalam.
Suasana hening sesaat, hanya terdengar desahan atau gesekan kursi.
Hatta mulai berbicara, suaranya rendah namun jelas, menjelaskan informasi yang baru ia terima tentang keresahan di Timur. Ia tidak memaksa, tetapi menyampaikan fakta dengan hati-hati. Tatapan Ki Bagus dan tokoh lainnya seperti Kasman Singodimedjo tertuju padanya, penuh pertimbangan. Terkadang salah satu dari mereka menyela, suaranya mungkin sedikit tinggi karena emosi, tetapi cepat reda. Ekspresi wajah mereka berganti-ganti antara kekecewaan, kekhawatiran, dan akhirnya penerimaan yang ikhlas.
Terlihat bagaimana mereka saling memandang, bukan sebagai lawan, tetapi sebagai rekan seperjuangan yang sama-sama terjepit dalam pilihan sulit. Pada akhirnya, ketika keputusan untuk menghapus tujuh kata diambil, ada keheningan yang berbeda—bukan keheningan kekalahan, tetapi keheningan pengorbanan yang disepakati bersama. Mereka kemudian bangkit, mungkin saling mengangguk atau berjabat tangan ringan, sebelum bergegas ke sidang PPKI yang akan mengukuhkan keputusan bersejarah itu.
Di ruangan itu, terpancar jelas bahwa yang terjadi adalah sebuah tindakan kolektif, sebuah gotong royong politik tingkat tinggi untuk menyelamatkan bayi Republik.
Terakhir
Jadi, pelajaran dari Piagam Jakarta itu jelas: Indonesia dibangun bukan dari keseragaman, melainkan dari keberanian untuk mengakui perbedaan dan menemukan titik temu. Semangat musyawarah, kesediaan berkorban, dan kepercayaan bahwa persatuan adalah harga matas yang ditunjukkan para pendiri bangsa adalah warisan yang tak ternilai. Dalam gegap gempita perbedaan pendapat di era digital sekarang, nilai-nilai kebersamaan itu justru lebih relevan dari sebelumnya—sebagai pengingat bahwa sebelum kita berselisih paham, kita adalah satu kesatuan yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
FAQ Lengkap
Apakah penghapusan “tujuh kata” berarti mengabaikan aspirasi umat Islam saat itu?
Tidak sama sekali. Prosesnya adalah negosiasi yang sangat hati-hati. Para tokoh Islam memahami bahwa persatuan nasional yang rapuh memerlukan pengorbanan. Sebagai bentuk kompensasi dan pengakuan, disepakati pembentukan Kementerian Agama dan prinsip bahwa presiden harus orang Indonesia asli yang beragama Islam (meski tidak tertulis), yang menunjukkan bahwa aspirasi tersebut tetap diakomodasi dalam bentuk lain.
Mengapa tokoh-tokoh Kristen dari Indonesia Timur begitu vokal menolak klausul tersebut?
Penolakan itu didasari kekhawatiran nyata bahwa klausul tersebut akan menjadi dasar hukum untuk memberlakukan hukum Islam secara nasional, yang akan mengubah status hukum dan hak mereka sebagai warga negara. Mereka adalah bagian integral dari Republik yang baru diproklamasikan dan ingin memastikan negara ini menjadi rumah bagi semua agama.
Apakah semangat kompromi 1945 masih mungkin diterapkan untuk menyelesaikan konflik sosial politik saat ini?
Sangat mungkin, tetapi memerlukan niat dan kemauan yang sama besarnya. Kunci dari kompromi 1945 adalah adanya tujuan bersama yang lebih besar (kemerdekaan dan persatuan bangsa) serta para pemimpin yang memiliki kewibawaan dan legitimasi untuk mengajak semua pihak berkorban. Prinsip musyawarah untuk mufakat dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kelompok adalah modal utama yang tetap berlaku.
Bagaimana jika kompromi itu gagal tercapai? Akankah Indonesia tetap utuh?
Sangat sulit dibayangkan. Kegagalan kompromi berpotensi memicu perpecahan vertikal sejak awal berdirinya negara, mungkin dengan wilayah-wilayah tertentu yang enggan bergabung atau bahkan terjadi konflik internal. Kompromi Piagam Jakarta adalah “jaminan” sosial pertama bahwa Republik Indonesia adalah milik bersama semua suku dan agama.