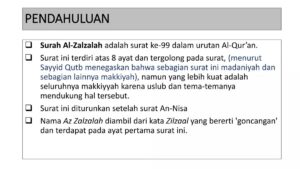Penyebab Pertempuran 10 November di Surabaya bukanlah sekadar letupan sesaat, melainkan akumulasi dari rentetan ketegangan, salah paham, dan prinsip yang beradu sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Bayangkan suasana kota pasca Agustus 1945, di mana semangat revolusi berkobar namun kekuasaan masih terpecah antara Barisan Keamanan Rakyat, laskar pemuda penuh gelora, dan sisa-sisa tentara Jepang yang bingung dengan statusnya. Dalam kekosongan kekuasaan yang genting itu, setiap tindakan bisa menjadi percik api, dan percik itulah yang akhirnya membakar semangat perlawanan Arek-arek Suroboyo hingga titik darah penghabisan.
Dinamika kompleks ini melibatkan tiga kekuatan utama dengan kepentingan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, pemuda dan rakyat Surabaya berjuang mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja mereka raih. Di sisi lain, pasukan Jepang yang kalah perang berusaha menjaga status quo hingga kedatangan Sekutu, sementara pihak Sekutu—dengan diboncengi niat kolonial Belanda—datang dengan misi yang justru dianggap mengancam kedaulatan Indonesia.
Tabel berikut memetakan gesekan kepentingan ketiganya:
Gejolak Sosial Pasca Proklamasi di Surabaya Sebagai Tanah Subur Konflik
Setelah gemuruh proklamasi 17 Agustus 1945 sampai ke Surabaya, euforia kemerdekaan tidak serta merta diikuti dengan tatanan kekuasaan yang mapan. Justru, kota pelabuhan terbesar kedua ini berubah menjadi kuali tekanan yang mendidih. Kekosongan otoritas menciptakan ruang bagi tiga kekuatan utama untuk saling tarik-ulur: Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang baru dibentuk dan masih mencari bentuk, berbagai laskar pemuda yang penuh semangat revolusioner namun kurang terkendali, serta sisa-sisa pasukan Jepang yang secara teknis kalah perang tetapi masih bersenjata lengkap dan menunggu kepastian dari Sekutu.
Situasi ini diperparah oleh kabar samar-samar tentang kedatangan pasukan Sekutu, yang di telinga rakyat seringkali disamakan dengan kembalinya penjajah Belanda. Suasana di jalanan adalah perpaduan antara harap, curiga, dan amarah yang siap meledak.
Dinamika kekuasaan bergerak sangat cepat dan kacau. BKR, cikal bakal TKR, berusaha menjalankan fungsi kepolisian dan ketertiban, tetapi kewibawaannya sering kali kalah oleh aksi-aksi spontan para pemuda. Kelompok-kelompok pemuda atau ‘arek-arek’ Surabaya, seperti PRI (Pemuda Republik Indonesia), membentuk laskar-laskar dengan senjata rampasan dari Jepang. Mereka melakukan perebutan kekuasaan atas instalasi-instalasi vital, terkadang melalui negosiasi, sering kali melalui konfrontasi. Di sisi lain, pasukan Jepang di bawah komando Vice Admiral Shibata Yaichiro, meski telah diperintahkan untuk menjaga status quo, berada dalam posisi sulit.
Mereka harus menjaga keamanan sambil menahan diri dari provokasi, sambil menunggu kedatangan Sekutu yang akan melucuti mereka. Ketegangan ini menciptakan insiden-insiden kecil hampir setiap hari, dari saling sikut di pos pemeriksaan hingga baku tembak yang tidak terduga, menjadikan Surabaya sebagai bubuk mesiu yang hanya membutuhkan percikan api.
Kelompok Utama dan Kepentingannya di Surabaya

Source: disway.id
Untuk memahami kompleksitas situasi, penting melihat peta kepentingan dari tiga aktor utama yang saling bersilangan di Surabaya antara September dan Oktober 1945. Masing-masing memiliki agenda dan cara bertindak yang berbeda, yang pada akhirnya saling berbenturan.
| Kelompok | Kepentingan Utama | Aksi Kunci (Sept-Okt ’45) | Persepsi terhadap Lawan |
|---|---|---|---|
| Pemuda/Arek-Arek Surabaya | Mempertahankan kemerdekaan secara total, melawan kembalinya kolonialisme dalam bentuk apapun. | Perampasan senjata Jepang, pengambilalihan gedung-gedung pemerintahan, demonstrasi massa, membentuk laskar. | Melihat Jepang sebagai musuh yang kalah, Sekutu/Belanda sebagai ancaman baru yang harus dihadapi. |
| Pasukan Jepang | Menjaga status quo hingga kedatangan Sekutu, melaksanakan tugas terakhir dengan menjaga keamanan tawanan Sekutu, menghindari konflik besar. | Pertahanan posisi di markas-markas, upaya melucuti diri sendiri secara terbatas, terkadang melakukan kekerasan untuk mencegah perampasan senjata. | Menganggap pemuda sebagai gerombolan tidak teratur yang mengancam keselamatan pasukan mereka dan tawanan. |
| Sekutu (Inggris) & Belanda (NICA) | Melucuti & memulangkan Jepang, membebaskan tawanan perang, mengembalikan pemerintahan sipil (dalam hal ini, Belanda). | Mendaratkan pasukan, berusaha menguasai titik-titik strategis, membawa serta personel NICA yang memicu kecurigaan. | Memandang situasi sebagai kekacauan yang dibuat oleh ekstremis, meremehkan kekuatan dan semangat juang rakyat Indonesia. |
Langkah-Langkah Provokatif yang Memanaskan Situasi
Sebelum insiden besar di Hotel Yamato, suasana sudah dipenuhi oleh serangkaian aksi dan reaksi yang saling memicu. Beberapa langkah provokatif dari berbagai pihak secara bertahap mengerek tensi ke level yang berbahaya.
- Penyebaran selebaran dan pengumuman dari pihak Sekutu/Belanda yang menyebut Republik Indonesia tidak ada, sehingga dianggap merendahkan kedaulatan yang baru saja diproklamasikan.
- Aksi perampasan senjata secara paksa oleh arek-arek Surabaya terhadap gudang dan konvoi Jepang, yang sering berakhir dengan baku tembak dan korban jiwa.
- Pembentukan dan mobilisasi massal laskar-laskar pemuda dengan orasi yang berapi-api, menanamkan sikap konfrontatif dan tidak percaya terhadap pihak asing mana pun.
- Kedatangan personel NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang menyusup dalam rombongan Sekutu, serta upaya mereka untuk menduduki kantor-kantor pemerintahan, yang memperkuat kecurigaan bahwa Sekutu adalah alat Belanda.
- Reaksi keras pasukan Jepang terhadap upaya perampasan senjata, seperti dalam insiden di Gedung Kenpeitai yang menewaskan banyak pemuda, yang menimbulkan dendam dan keinginan balas dendam.
Suasana Hati Seorang Pemuda Surabaya
Angin September di Surabaya terasa panas dan berdebu, membawa bisik-bisik yang saling bertentangan. Di sudut-sudut kota, bendera merah putih berkibar gagah, tapi di telinga terdengar desas-desus tentang kapal perang Sekutu yang mendekat. Senjata yang kami rampas dari gudang Jepang terasa berat di pundak, bukan hanya berat besinya, tapi berat tanggung jawabnya. Setiap malam, rapat-rapat di kampung dipenuhi suara sumbang: ada yang bilang harus damai, lebih banyak yang teriak harus siap tempur. Rasanya seperti menunggu hujan badai yang sudah terlihat awan hitamnya di cakrawala. Kami tahu sesuatu akan terjadi, kami hanya tidak tahu kapan. Dan di tengah semua ini, ada satu keyakinan yang membara: kami tidak akan membiarkan mereka menginjak-injak kemerdekaan ini, tidak lagi.
Insiden Pengibaran Bendera Belanda di Hotel Yamato Sebagai Pemicu Emosi Publik
Jika gejolak sosial pasca proklamasi menciptakan bubuk mesiu, maka insiden di Hotel Yamato pada 19 September 1945 adalah percikan apinya. Hotel yang terletak di pusat kota itu, yang sebelumnya bernama Hotel Oranje, menjadi simbol sentimen kolonial. Setelah Jepang menyerah, hotel itu ditempati oleh orang-orang Belanda yang dibebaskan dari kamp tawanan, termasuk seorang pejabat bernama Mr. W.V.Ch. Ploegman.
Pada pagi hari tanggal 19 September, sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera Belanda (merah-putih-biru) di puncak menara hotel, menggantikan bendera Indonesia yang sebelumnya berkibar di sana. Tindakan ini bukan sekadar kesalahan protokol, melainkan sebuah pernyataan politik yang terang-terangan dan sangat provokatif di tengah kota yang sedang bergelora semangat kemerdekaan.
Kabar tentang bendera biru-putih-merah yang berkibar dengan angkuhnya segera menyebar bagai kobaran api. Massa dari berbagai penjuru kota bergerak memadati Tunjungan, mengepung Hotel Yamato. Suasana berubah dari penasaran menjadi marah. Perundingan pun dilakukan. Beberapa perwakilan pemuda, termasuk Hariyono dan Koesno Wibowo, masuk ke hotel untuk menuntut bendera Belanda diturunkan.
Negosiasi dengan Ploegman berlangsung alot dan tegang, bahkan berujung pada keributan di dalam ruangan yang menyebabkan Ploegman tewas. Di luar, massa yang semakin tidak sabar mulai mendobrak pintu dan menerjang ke dalam. Tekanan dari ribuan orang yang marah membuat situasi tidak lagi terkendali. Pada puncaknya, seorang pemuda bernama Koesno Wibowo, dengan risiko nyawanya, memanjat ke puncak menara hotel dan merobek bagian biru bendera Belanda, menyisakan warna merah dan putih yang kemudian dikibarkan kembali.
Sorak-sorai massa menggema di seluruh penjuru kota.
Pihak-Pihak dalam Insiden Hotel Yamato
| Pihak | Motivasi | Tindakan Spesifik | Dampak Langsung |
|---|---|---|---|
| Kelompok Belanda (Mr. Ploegman dkk) | Menunjukkan klaim kedaulatan Belanda dan memprovokasi untuk menguji reaksi pihak Indonesia. | Mengibarkan bendera Belanda di menara hotel, bersikeras menolak menurunkannya saat dinegosiasi. | Memicu kemarahan massa, menjadikan Hotel Yamato sebagai simbol permusuhan, dan memulai eskalasi konflik terbuka. |
| Arek-Arek Surabaya (Massa) | Mempertahankan kehormatan bendera merah putih sebagai simbol kedaulatan yang tidak boleh dinistakan. | Berkumpul, mendesak, mendobrak masuk ke hotel, dan memberikan tekanan fisik serta psikologis. | Menunjukkan kekuatan massa yang solid dan kemauan untuk bertindak langsung melawan simbol kolonial. |
| Perwakilan Pemuda (Hariyono, Koesno Wibowo) | Menyelesaikan insiden melalui jalur diplomasi terlebih dahulu, tetapi siap mengambil tindakan tegas. | Berunding di dalam hotel, terlibat keributan dengan Ploegman, dan memanjat untuk merobek bendera. | Menjadi pahlawan simbolik aksi tersebut; aksi perobekan menjadi legenda yang memompa semangat juang. |
| Pasukan Keamanan Indonesia (BKR/Laskar) | Mengamankan situasi dan mencoba mencegah korban jiwa yang lebih besar dari kerumunan massa. | Berusaha mengatur kerumunan, meski kewalahan, dan akhirnya mengamankan area pasca insiden. | Menunjukkan keterbatasan otoritas formal dalam mengendalikan aksi massa yang spontan dan emosional. |
Konsekuensi Langsung Insiden Hotel Yamato
Insiden ini bukan sekadar kerusuhan lokal. Ia menjadi pukulan telak terhadap hubungan awal antara pihak Indonesia dengan pasukan Sekutu (Inggris) yang baru akan mendarat. Bagi Inggris, yang misi awalnya adalah melucuti Jepang dan menjaga ketertiban, aksi massa yang brutal terhadap warga sipil Belanda dilihat sebagai bukti bahwa Surabaya dikuasai oleh “ekstremis” dan “gerombolan” yang berbahaya. Kepercayaan yang sudah tipis pun langsung runtuh.
Insiden ini mempersulit misi Sekutu dalam beberapa hal: pertama, menciptakan prasangka buruk yang akan memengaruhi setiap interaksi berikutnya; kedua, memaksa Sekutu untuk lebih berhati-hati dan mungkin lebih agresif dalam pendekatan; dan ketiga, mengukuhkan dalam benak arek-arek Surabaya bahwa Sekutu adalah musuh karena membela kepentingan Belanda. Jalan untuk dialog damai menjadi sangat sempit setelah bendera biru itu dikibarkan.
Momen Perobekan Bendera di Puncak Menara
Di puncak menara Hotel Yamato yang menjulang, angin sore bertiup kencang, mengerek-erek kain bendera Belanda yang berkibar sombong. Koesno Wibowo, dengan tubuh yang melekat erat pada besi tua menara, tangan dan kakinya mencari pegangan yang pasti. Di bawahnya, lautan manusia yang memenuhi lapangan dan atap-atap rumah terlihat seperti kumpulan titik yang bergerak-gerak, teriakannya naik seperti desis angin. Wajahnya yang penuh keringat memantulkan tekad baja, mata tajamnya tertuju pada sepetak kain biru di ujung tiang.
Dengan satu tangan mencengkeram kuat, tangan lainnya meraih, menjangkau, dan akhirnya mencengkeram ujung kain biru itu. Suara robekan yang keras mungkin tenggelam oleh teriakan di bawah, tapi aksinya terlihat jelas: sebuah tarikan kuat, dan warna biru yang melambangkan kerajaan Belanda itu terpisah, terkoyak, dan akhirnya terlepas, diterbangkan angin seperti sampah yang tak berguna. Yang tersisa di tiang, berkibar dengan bangganya di langit Surabaya, adalah sepotong kain merah dan putih.
Sorak-sorai yang meledak dari ribuan mulut seakan mengguncang fondasi hotel tua itu, sebuah deklarasi tanpa suara bahwa tanah ini telah merdeka.
Kematian Brigadir Jenderal Mallaby dan Titik Tanpa Kembali Menuju Pertempuran
Setelah insiden Hotel Yamato, Surabaya memasuki periode ketegangan yang sangat tinggi dengan pasukan Inggris yang telah mendarat. Upaya gencatan senjata sempat dicoba, tetapi suasana penuh kecurigaan. Di tengah upaya rapuh ini, tewasnya Brigadir Jenderal Aubertin Walter Sothern Mallaby, komandan Brigade Infanteri ke-49 Inggris, pada 30 Oktober 1945 menjadi titik kritis yang mengubah segalanya. Kematiannya terjadi dalam keadaan yang sangat membingungkan dan kontroversial, di dekat Jembatan Merah.
Satu versi menyatakan mobilnya dikepung oleh massa yang marah, dan sebuah granat meledak di dalam atau dekat mobilnya, menewaskan Mallaby serta beberapa anak buahnya. Versi lain dari pihak Indonesia menyebutkan bahwa ledakan berasal dari tembakan yang mengenai persediaan amunisi di dalam mobil Mallaby, atau bahkan dari tembakan pihak Inggris sendiri yang panik. Kebenaran absolut sulit dipastikan hingga hari ini, yang jelas, kematian seorang perwira senior Inggris di tengah kota yang diduduki pasukannya sendiri adalah sebuah bencana diplomatik dan militer.
Pertempuran 10 November di Surabaya dipicu oleh kemarahan rakyat atas penghinaan terhadap bendera dan tewasnya Brigadir Mallaby. Seperti menyelesaikan teka-teki sejarah, kita juga bisa mengurai sebuah soal logaritma yang menarik, misalnya Menentukan nilai 6log28 dari 2log3 = a dan 2log7 = b , di mana strategi dan ketelitian dibutuhkan layaknya strategi perang. Nilai perjuangan dalam sejarah pun, seperti halnya nilai logaritma tadi, memerlukan analisis mendalam untuk benar-benar kita pahami maknanya.
Kontroversi seputar kematian Mallaby semakin memperkeruh upaya gencatan senjata. Sebelum insiden, sebenarnya telah ada kesepakatan untuk menghentikan tembak-menembak. Mallaby sendiri sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan pemimpin Indonesia guna memperkuat kesepakatan tersebut. Kematiannya di tengah misi damai ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah itu pembunuhan berencana, sebuah insiden tragis akibat kesalahpahaman, atau hasil provokasi dari pihak yang tidak menginginkan perdamaian? Kendala dalam gencatan senjata pun menjadi nyata: kurangnya komunikasi yang efektif antara komando Inggris dengan laskar-laskar di lapangan, tingkat disiplin yang berbeda-beda di antara milisi Indonesia, dan emosi massa yang sudah memuncak.
Kepercayaan, yang menjadi dasar setiap gencatan senjata, hancur seketika bersama dengan mobil yang terbakar di dekat Jembatan Merah.
Kronologi Tragedi di Jembatan Merah
Rangkaian peristiwa pada 30 Oktober 1945 bergerak cepat dari upaya damai menuju tragedi. Berikut adalah timeline yang merinci momen-momen kritis sekitar kematian Brigjen Mallaby.
- Sore hari, terjadi insiden baku tembak antara pasukan Inggris dan pejuang Indonesia di sekitar Jembatan Merah, melanggar kesepakatan gencatan senjata yang baru saja disepakati.
- Mendengar hal ini, Brigjen Mallaby yang berada di markas besar Inggris di Gedung Internatio memutuskan untuk turun tangan langsung. Ia ingin mencegah konflik kecil meluas.
- Mallaby berangkat menuju lokasi dengan konvoi, termasuk mobil Buick yang dikemudikan oleh sopir pribadinya.
- Sesampainya di dekat Jembatan Merah, situasi masih tegang. Mallaby turun dari mobilnya untuk berunding dengan para pejuang Indonesia yang mengepung area.
- Perundingan berlangsung singkat di tengah kerumunan massa yang semakin banyak dan emosional. Mallaby kemudian memutuskan untuk kembali ke mobilnya.
- Pada saat ia naik atau baru saja masuk ke dalam mobil Buick, sebuah ledakan keras terjadi dari dalam atau sangat dekat dengan kendaraan tersebut.
- Mobil terbakar dengan cepat. Mallaby, yang terluka parah, tewas di tempat bersama beberapa anggota pasukannya. Kebakaran dan kekacauan membuat evakuasi dan pertolongan menjadi sangat sulit.
Reaksi Inggris dan Jalan Menuju Ultimatum
Reaksi pihak Inggris terhadap kematian Mallaby bisa ditebak: shock dan murka. Seorang brigadir jenderal yang tewas dalam tugas dianggap sebagai penghinaan besar terhadap martabat militer Inggris. Komando tertinggi di Jawa, di bawah Letnan Jenderal Sir Philip Christison, dan terutama pengganti Mallaby, Brigadir Jenderal Robert Loder-Symonds, melihat ini sebagai bukti bahwa pihak Indonesia tidak dapat diajak berunding dan hanya memahami bahasa kekuatan.
Dari sini, logika eskalasi militer berjalan: untuk membalas kematian pimpinan mereka, mendisiplinkan kota yang dianggap memberontak, dan menyelesaikan misi mereka dengan cara yang tegas. Ultimatum 10 November yang terkenal itu bukan muncul dari ruang hampa. Ia adalah produk langsung dari kemarahan, keinginan balas dendam, dan penilaian strategis bahwa hanya dengan menunjukkan kekuatan penuh, Inggris bisa menguasai Surabaya. Tragedi Mallaby memberikan alasan dan pembenaran moral bagi Inggris untuk melancarkan serangan besar-besaran.
Analisis: Titik Tanpa Kembali
Kematian Brigjen Mallaby bukan sekadar insiden kematian seorang perwira tinggi. Ia berfungsi sebagai ‘point of no return’ yang secara permanen memutus segala jalur diplomasi yang tersisa. Sebelum peristiwa ini, meski penuh ketegangan, masih ada ruang untuk negosiasi dan kompromi, sebagaimana upaya gencatan senjata menunjukkan. Namun, setelah mobil Mallaby meledak dan terbakar, dinamika berubah total. Bagi Inggris, ini adalah casus belli—alasan perang yang sah di mata mereka. Segala bentuk pertimbangan politik dan kehati-hatian tersapu oleh kewajiban kode militer untuk membalas dan menegakkan wibawa. Bagi pihak Indonesia, kematian Mallaby menjadi simbol bahwa Inggris bukanlah penengah, melainkan musuh yang akan menghancurkan mereka. Dengan hilangnya tokoh yang dianggap masih bisa diajak berunding dari pihak Inggris, pilihan yang tersisa hanyalah perlawanan total. Jalur damai tertutup rapat, dan satu-satunya jalan yang terbuka adalah jalan pertempuran yang akan menentukan harga diri kedua belah pihak.
Ultimatum 10 November dan Solidifikasi Semangat Perlawanan Rakyat Surabaya
Pasca kematian Mallaby, atmosfer di Surabaya bagai ditangguhkan antara ketakutan dan kemarahan. Semua mata tertuju pada reaksi Inggris. Jawabannya datang pada 9 November 1945: sebuah ultimatum keras dari Mayor Jenderal Robert Mansergh, yang menggantikan Loder-Symonds. Isinya sederhana namun mustahil: seluruh pemimpin Indonesia dan penduduk Surabaya harus menyerahkan senjata mereka, dengan tangan di atas kepala, paling lambat pukul 06.00 pagi tanggal 10 November.
Mereka juga harus berbaris ke tempat yang ditentukan untuk memberi hormat kepada bendera Inggris. Jika tidak, Inggris akan menggempur kota dengan kekuatan penuh darat, laut, dan udara. Ultimatum ini disebarkan melalui selebaran udara dan pengumuman. Bagi Inggris, ini adalah tuntutan logis untuk menegakkan ketertiban. Bagi arek-arek Surabaya, ini adalah penghinaan yang tak terkira, sebuah perintah untuk menyerah dan dipermalukan di tanah mereka sendiri.
Pertempuran 10 November di Surabaya meletus bukan tanpa sebab; semangat juang rakyat melawan Sekutu adalah wujud nyata dari tekad mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Semangat itu sendiri berakar dari nilai-nilai luhur yang dirumuskan dalam Sejarah Singkat Lahirnya Pancasila , yang menjadi fondasi ideologis bangsa. Dengan demikian, peristiwa heroik di Surabaya itu dapat dilihat sebagai aksi kolektif untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar negara yang telah disepakati bersama, menjadikannya babak penting dalam perjalanan kedaulatan Indonesia.
Respons dari berbagai elemen masyarakat Surabaya terhadap ultimatum itu luar biasa: penolakan bulat. Ultimatum itu justru menjadi perekat yang mempersatukan berbagai kelompok yang sebelumnya mungkin terpecah—Tentara Keamanan Rakyat (TKR), laskar-laskar pemuda seperti PRI, ulama, tokoh masyarakat, hingga rakyat biasa. Semua perbedaan tenggelam oleh satu tujuan: melawan. Ultimatum Inggris tidak menciptakan ketakutan yang melumpuhkan, melainkan sebuah kemarahan yang memantik tekad baja.
Rakyat Surabaya memilih untuk berdiri tegak dan bertarung, meski mereka sadar senjata mereka tidak sebanding. Keputusan itu bukanlah keputusan nekad semata, melainkan pilihan sadar untuk mempertahankan harga diri dan kedaulatan yang lebih berharga daripada nyawa.
Peta Reaksi terhadap Ultimatum 10 November, Penyebab Pertempuran 10 November di Surabaya
| Komponen Perjuangan | Bentuk Reaksi | Peran dalam Solidifikasi | Dampak terhadap Semangat Juang |
|---|---|---|---|
| TKR dan Komandan Militer (seperti Doel Arnowo, Moestopo) | Menolak ultimatum, menyusun strategi pertahanan seadanya, mengkoordinasi posisi pasukan meski dengan senjata terbatas. | Memberikan kerangka organisasi dan komando dalam pertahanan, meski tidak semua laskar tunduk sepenuhnya. | Memberikan kesan bahwa perlawanan akan terstruktur, bukan sekadar amuk massa. |
| Laskar Pemuda (PRI, BPRI, dll) | Menyiapkan barikade, menyebarkan semangat perlawanan ke basis-basis, menolak keras untuk menyerahkan senjata. | Menjadi ujung tombak perlawanan di garis depan dan motor penggerak semangat di tingkat akar rumput. | Semangat revolusioner mereka yang membara menjadi inspirasi dan tenaga utama di medan tempur. |
| Ulama dan Tokoh Agama (seperti KH. Hasyim Asy’ari dari luar kota) | Mengeluarkan seruan atau fatwa yang menyatakan perjuangan melawan penjajah sebagai jihad, wajib hukumnya. | Memberikan legitimasi religius dan spiritual pada perlawanan, mengubahnya dari perang politik menjadi kewajiban suci. | Memantapkan hati yang ragu, memberikan keyakinan bahwa gugur di medan perang adalah syahid. |
| Tokoh Masyarakat & Rakyat Biasa | Membantu logistik, menyiapkan dapur umum, merawat luka, atau bahkan mengambil senjata sederhana untuk ikut bertahan. | Membentuk jaringan dukungan logistik dan moral yang membuat perlawanan bisa bertahan lebih dari sehari. | Menunjukkan bahwa perlawanan adalah perang rakyat total, bukan hanya perang tentara dan laskar. |
Proses Pengambilan Keputusan untuk Melawan
Di balik tekad bulat rakyat, terdapat proses pengambilan keputusan yang intens di kalangan pemimpin perjuangan Surabaya. Rapat-rapat digelar di tengah malam, di tempat yang dirahasiakan. Suasana rapat penuh debat: ada yang realistis tentang kekuatan senjata Inggris, ada yang berapi-api menolak kompromi. Namun, suara untuk menyerah sama sekali tidak ada. Pertimbangannya bergeser dari “apakah kita bisa menang?” menjadi “bagaimana kita bisa membuat mereka membayar mahal untuk setiap jengkal tanah Surabaya?”.
Keputusan akhir untuk menolak ultimatum dan siap bertempur sampai titik darah penghabisan diambil dengan penuh kesadaran akan konsekuensinya. Mereka tahu kota mungkin akan hancur, banyak yang akan gugur. Tapi mereka juga yakin bahwa menyerah berarti mengkhianati jiwa revolusi dan membiarkan kemerdekaan yang baru diraih direnggut kembali. Keputusan itu kemudian disosialisasikan melalui jaringan laskar dan tokoh masyarakat: besok pagi, tidak ada yang menyerah.
Semua siap untuk pertempuran yang tidak seimbang, namun penuh makna.
Kekuatan Kata-Kata: Pidato Bung Tomo di Udara
Malam sebelum pertempuran, udara malam di Surabaya terasa pekat oleh ketegangan dan antisipasi. Dari sebuah pemancar radio sederhana, suara yang keras, berapi-api, dan penuh emosi memecah kesunyian. Itu adalah suara Bung Tomo. Tanpa gambar, hanya melalui suara yang disiarkan ke seluruh penjuru kota, ia melukiskan dengan kata-kata. Suaranya naik turun, dari bisikan yang menggetarkan hingga pekikan yang membakar jiwa.
Ia menyebut tentara Inggris sebagai “setan dan antek-anteknya”, menyerukan bahwa perlawanan ini adalah jihad, panggilan suci. Setiap kalimatnya seperti pentungan yang memukul gong semangat di dalam hati setiap pendengarnya. Di rumah-rumah, di pos-pos penjagaan, di markas laskar, orang berkumpul mendengarkan. Wajah-wajah yang sebelumnya diliputi kecematan berangsur berubah. Mata yang tadi lesu mulai menyala.
Ketakutan yang membeku dicairkan oleh aliran kata-kata yang panas, lalu ditempa menjadi sebuah tekad kolektif yang keras bagai baja. Pidato itu tidak memberikan strategi militer, tetapi ia memberikan sesuatu yang lebih penting: jiwa untuk bertempur. Esok harinya, ketika meriam pertama mengguruh, arek-arek Surabaya maju bukan lagi sebagai kerumunan yang takut, tetapi sebagai pejuang yang yakin akan kebenaran perjuangannya, dengan teriakan “Allahu Akbar!” dan “Merdeka!” yang bergema sebagai jawaban atas ultimatum Inggris.
Konfigurasi Militer dan Logistik Inggris yang Memicu Konfrontasi Tak Terhindarkan
Untuk memahami mengapa Pertempuran 10 November terjadi dalam skala begitu masif, kita perlu melihat persiapan dan persepsi militer Inggris. Pasukan Inggris yang ditugaskan di Jawa, khususnya Brigade Infanteri ke-49 di bawah Mallaby, adalah pasukan veteran Perang Dunia II yang baru saja merasakan kemenangan. Mereka datang dengan misi resmi RAPWI (Recovery of Allied Prisoners of War and Internees): melucuti Jepang dan memulangkan tawanan perang Sekutu.
Namun, dalam praktiknya, mereka juga membawa serta agenda politik untuk mengembalikan administrasi Belanda (NICA). Persepsi awal mereka terhadap situasi di Surabaya dipenuhi oleh bias kolonial: mereka melihat perlawanan rakyat bukan sebagai gerakan nasionalis yang sah, melainkan sebagai aksi “gerombolan” atau “ekstremis” yang dipimpin oleh mantan kolaborator Jepang. Persepsi ini membuat mereka meremehkan kekuatan dan semangat lawan, serta cenderung memilih pendekatan yang otoriter dan konfrontatif.
Komposisi pasukan Inggris sendiri dirancang untuk pertempuran konvensional, bukan untuk menghadapi perang gerilya dan perlawanan rakyat total. Mereka mengandalkan kekuatan tempur yang terorganisir, dukungan artileri berat, tank, serta dukungan laut dan udara dari kapal perang seperti HMS Sussex. Logistik mereka sangat superior, dirancang untuk pertempuran frontal. Namun, justru pendekatan militeristik inilah yang memicu konfrontasi tak terhindarkan. Ketika mereka menghadapi penolakan dan perlawanan sporadis, respon yang mereka anggap tepat adalah menunjukkan kekuatan yang lebih besar, bukan berdialog.
Esensi misi mereka pun bergeser dari tugas kemanusiaan (RAPWI) menjadi tugas penaklukan militer untuk “menertibkan” sebuah kota yang dianggap memberontak. Pergeseran misi ini, yang dipicu oleh kematian Mallaby, membuat segala persiapan logistik dan taktik mereka dialihkan untuk satu tujuan: menghancurkan perlawanan di Surabaya.
Kesalahan Intelijen dan Penilaian Politik Inggris
Kegagalan Inggris dalam membaca situasi Surabaya berakar pada beberapa kesalahan intelijen dan penilaian politik yang fatal.
- Meremehkan Semangat Juang: Intelijen Inggris gagal memahami bahwa kemerdekaan bukan hanya isu politik elite, tetapi telah menyentuh rasa harga diri dan nasionalisme rakyat kecil. Mereka mengira dengan menangkap beberapa “pemimpin”, perlawanan akan runtuh.
- Mengabaikan Peran Ulama dan Simbol Agama: Mereka tidak memperhitungkan bahwa fatwa jihad dari ulama akan mengubah konflik menjadi perang suci, yang membuat pejuang Indonesia lebih berani dan rela mati syahid.
- Kesalahan Identifikasi Musuh: Inggris sering menyamakan semua laskar dan pejuang sebagai “gerombolan” yang tidak terlatih, tanpa melihat adanya elemen mantan tentara PETA dan Heiho yang memiliki pengalaman militer dasar.
- Politik yang Kaku: Keterikatan mereka pada komitmen untuk membantu Belanda memulihkan kekuasaannya membuat mereka menutup mata terhadap realitas politik baru Republik Indonesia, sehingga menolak berunding dengan pemerintah Republik sebagai pihak yang setara.
- Menganggap Tekanan Militer Cukup: Mereka percaya bahwa ultimatum dan demonstrasi kekuatan (seperti overflight pesawat tempur) akan membuat rakyat Surabaya takut dan menyerah, tidak memahami bahwa tekanan justru memantik perlawanan yang lebih gigih.
Persiapan Inggris dan Determiniasi Arek-Arek Surabaya
Persiapan logistik dan taktik penyerangan Inggris justru menjadi bumerang yang memperkuat determinasi arek-arek Surabaya. Pengerahan ribuan pasukan, puluhan tank, dan kapal perang di lepas pantai menunjukkan betapa seriusnya ancaman itu. Namun, bagi pemuda Surabaya, ini bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan sebuah tantangan yang membanggakan: mereka, rakyat jelata dengan senjata seadanya, akan menghadapi salah satu pasukan terkuat di dunia. Persiapan Inggris yang masif itu justru menjadi bukti nyata bahwa mereka adalah penjajah yang ingin kembali menjajah.
Setiap tank yang bergerak, setiap pesawat yang terbang rendah, semakin menyatukan hati warga Surabaya untuk bertahan mati-matian. Mereka menyiapkan pertahanan dari rumah ke rumah, membuat lubang-lubang perlindungan, dan menggunakan taktik gerilya urban yang justru menetralisir keunggulan teknologi Inggris. Logistik superor Inggris menghadapi logistik semangat juang yang tak terukur dari rakyat Surabaya.
Ringkasan: Kombinasi Superioritas dan Balas Dendam
Keputusan final Inggris untuk melancarkan serangan besar-besaran pada 10 November dibentuk oleh dua faktor yang saling menguatkan: rasa superioritas militer dan kewajiban untuk membalas kematian Mallaby. Di satu sisi, doktrin militer mereka yang kolonial mengajarkan bahwa pemberontakan harus dihancurkan dengan kekuatan telak untuk memberi pelajaran. Di sisi lain, kematian seorang brigadir jenderal adalah aib yang harus ditebus dengan kemenangan militer yang tak terbantahkan. Kombinasi ini menciptakan sebuah logika operasi yang brutal: Surabaya harus dihancurkan untuk ditundukkan, sekaligus untuk menunjukkan kepada seluruh Indonesia (dan dunia) bahwa Inggris tidak bisa diremehkan. Mereka masuk ke pertempuran dengan keyakinan akan kemenangan cepat, tetapi gagal menghitung bahwa lawan mereka tidak berperang untuk menang secara militer belaka, melainkan untuk membuktikan bahwa kemerdekaan mereka tidak bisa diinjak-injak. Inilah yang membuat konfrontasi itu tak terhindarkan dan begitu dahsyat akibatnya.
Akhir Kata
Dari seluruh rangkaian peristiwa itu, dapat disimpulkan bahwa Pertempuran 10 November adalah konsekuensi yang tak terelakkan dari benturan antara semangat revolusi yang tak terbendung dengan logika kolonial yang kaku. Bukan hanya sekadar respons atas ultimatum atau pembunuhan seorang jenderal, pertempuran ini adalah puncak dari semua rasa frustasi, harga diri yang terluka, dan tekad bulat untuk berdaulat. Surabaya menjadi bukti bahwa ketika sebuah bangsa sudah memutuskan untuk merdeka, tidak ada kekuatan senjata apa pun yang bisa memadamkan api perjuangan di hati rakyatnya.
Pelajaran dari Surabaya 1945 tetap relevan hingga hari ini: kemerdekaan adalah harga mati yang diperjuangkan dengan keberanian kolektif. Semangat “Merdeka atau Mati” yang dikobarkan Bung Tomo dan ribuan pejuang lainnya bukan sekadar slogan, melainkan napas dari setiap warga yang memilih berdiri tegak di atas puing-puing kota mereka daripada hidup berlutut. Pertempuran ini, dengan segala penyebabnya, mengukir sebuah narasi heroik bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan selalu memiliki akar yang kuat di dalam sanubari manusia yang merdeka.
Pertanyaan yang Sering Diajukan: Penyebab Pertempuran 10 November Di Surabaya
Apakah Pertempuran 10 November bisa dihindari?
Dengan melihat eskalasi ketegangan yang terjadi sejak September, peluang untuk menghindari pertempuran terbuka sangat kecil. Titik tanpa kembali sudah tercapai setelah tewasnya Brigjen Mallaby dan dikeluarkannya ultimatum yang tidak bisa diterima oleh pihak Indonesia.
Apa peran Bung Tomo sebelum pertempuran terjadi?
Bung Tomo bukan hanya orator di radio. Sebelum 10 November, ia aktif memobilisasi pemuda, mengkoordinasi laskar, dan menjadi juru bicara perlawanan yang efektif dalam membangun narasi perjuangan dan menyatukan berbagai elemen masyarakat Surabaya.
Bagaimana kondisi logistik dan persenjataan pejuang Surabaya?
Pejuang Surabaya sangat minim dalam persenjataan modern. Mereka mengandalkan senjata rampasan dari Jepang, bom molotov, bambu runcing, serta taktik gerilya urban. Logistik pun mengandalkan dukungan spontan dari warga, berbeda jauh dengan pasukan Inggris yang dilengkapi persenjataan berat dan dukungan udara serta laut.
Mengapa Inggris begitu keras dalam ultimatumnya?
Ultimatum yang keras dilatarbelakangi oleh kombinasi rasa superioritas militer, kewajiban untuk membalas kematian Mallaby, serta penilaian intelijen yang keliru yang meremehkan semangat dan kemampuan perlawanan rakyat Surabaya.
Apakah ada upaya perundingan setelah ultimatum dikeluarkan?
Upaya perundingan sesungguhnya sudah sangat sulit dilakukan setelah ultimatum. Pihak Indonesia, yang diwakili oleh Gubernur Soerjo dan pemimpin lainnya, telah memilih untuk menolak ultimatum karena menganggapnya sebagai penghinaan terhadap kedaulatan, sehingga jalan perang adalah satu-satunya pilihan yang tersisa.